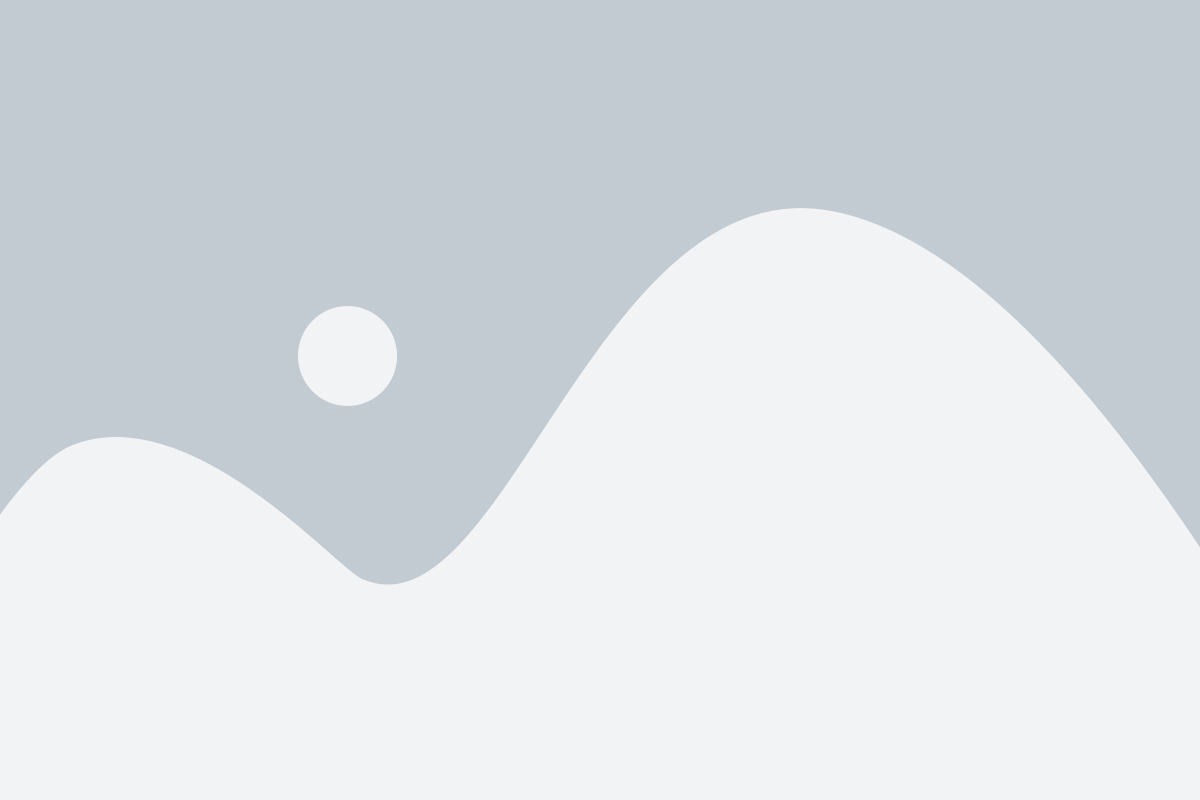Dalam suatu forum diskusi dengan wartawan ekonomi dan moneter akhir minggu, Dirut PT PLN Dahlan Iskan melemparkan gagasan ”listrik gratis bagi orang miskin”.

Fabby Tumiwa
(Artikel opini ini telah dipublikasikan di harian Kompas, halaman 7: http://cetak.kompas.com.)
Dalam suatu forum diskusi dengan wartawan ekonomi dan moneter akhir minggu, Dirut PT PLN Dahlan Iskan melemparkan gagasan ”listrik gratis bagi orang miskin”.
Pernyataan serupa disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR. Listrik gratis untuk orang miskin dapat mengurangi pendapatan PLN Rp 1,5 triliun. Jika kenaikan diberikan pada kelompok pelanggan rumah tangga (RT) lain, pendapatan tambahan minimal Rp 15 triliun. Andai kata perhitungannya tepat, opsi ini lebih menguntungkan PLN dibandingkan dengan opsi kenaikan 10-15 persen, yang memberikan tambahan pendapatan Rp 6 triliun-Rp 7 triliun per tahun.
Ide ini bukan hal baru. Afrika Selatan telah mempraktikkan dengan cukup berhasil hampir 10 tahun. Tahun 2001, Pemerintah Afrika Selatan menetapkan kebijakan pemberian air dan listrik gratis bagi warga miskin. Kebijakan yang disebut ”Free Basic Electricity” tersebut memberikan RT miskin 50 kilowatt-jam tenaga listrik yang berasal dari jaringan listrik (grid) secara gratis setiap bulan.
Pemakaian listrik yang lebih tinggi dari kuota itu dikenai tarif berundak. Kuota 50 kilowatt-jam ditentukan berdasarkan konsumsi rata-rata 54 persen dari 6,4 juta pelanggan RT. Kebijakan listrik gratis hanya berlaku bagi RT yang memenuhi kriteria miskin. Pelanggan yang tidak masuk kategori ini harus membayar tarif non-subsidi sehingga terjadi subsidi silang antar-golongan.
Sejumlah prasyarat
Apakah kebijakan seperti ini bisa diterapkan di Indonesia? Bisa saja, tetapi dengan sejumlah prasyarat, kondisi, dan pertimbangan. Pertama, perlu filosofi dan tujuan kebijakan jelas dan jangka panjang, tidak seumur jagung. Filosofi yang mendasari Afrika Selatan mengambil kebijakan ini: listrik adalah pelayanan dasar hakiki, kebutuhan dasar warga masyarakat, sehingga akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin harus dijamin. Rendahnya kemampuan ekonomi tak boleh menghalangi masyarakat miskin memperoleh pelayanan listrik yang baik.
Kedua, perlu kejelasan definisi ”miskin”. Penggunaan kata ”miskin” dalam debat kenaikan TDL akhir-akhir ini sesungguhnya bias dan salah kaprah. Baik eksekutif maupun DPR memakai definisi ”miskin” untuk pelanggan listrik 450 VA dan atau 900 VA. Masyarakat yang telah mendapatkan akses listrik dikategorikan orang miskin, padahal masyarakat miskin sesungguhnya adalah yang berpendapatan sangat rendah dan masih belum terjangkau listrik, bahkan pada praktiknya mengeluarkan biaya mahal untuk mendapatkan penerangan dengan kualitas yang sangat buruk. Mereka inilah justru ditinggalkan eksekutif, DPR, dan PLN dalam hiruk-pikuk perdebatan kenaikan TDL.
Mayoritas sambungan listrik RT sebelum 1990-an dilakukan dengan daya tersambung 450 VA. Seiring korporatisasi PLN yang salah satunya bertujuan mengurangi beban subsidi, terjadi pembatasan kuota sambungan 450 VA. Maka, alokasi sebagian besar sambungan baru pada akhir 1990-an naik menjadi 900 VA dan saat ini mayoritas kuota sambungan baru yang disediakan PLN adalah 1.300 VA. Hanya sedikit kuota sambungan 450 VA tersedia. Menilik sejarah tersebut, tidak heran jika masih cukup banyak pelanggan dari tahun 1970-an yang masih mempertahankan sambungan 450 VA dan 900 VA. Jumlahnya lebih dari setengah total pelanggan RT. Sangat mungkin sebagian mereka RT berpendapatan rendah, tetapi kurang tepat jika dikategorikan RT miskin jika dibandingkan dengan orang miskin yang sebenarnya berpendapatan rendah dan tidak memiliki akses listrik.
Ketiga, masalah utama adalah rendahnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kelistrikan. Selama 15 tahun terakhir rasio elektrifikasi tumbuh kurang dari 1 persen per tahun. Bagi masyarakat miskin yang belum terjangkau listrik, kendala utama adalah ketersediaan dan biaya sambungan listrik, bukan tarif listrik. Biaya pasang baru dan instalasi jaringan listrik dalam rumah yang bisa mencapai Rp 1 juta-Rp 2 juta sejatinya sulit terjangkau masyarakat miskin.
Selain itu, kebijakan PLN yang membatasi kuota sambungan daya rendah, seperti 450 VA dan 900 VA, mengakibatkan masyarakat miskin tidak memiliki banyak pilihan. Andai kata sambungan baru tersedia, mereka harus menyambung listrik dengan daya terpasang lebih tinggi, misalnya 1.300 VA. Dampaknya tagihan listrik bulanan akan membebani mereka karena TDL untuk daya tersambung non-450 VA lebih mahal dari 450 VA.
Keempat, ketersediaan infrastruktur terbatas. Rendahnya kapasitas terpasang pembangkit baru dan terbatasnya jaringan distribusi tegangan rendah menyebabkan masyarakat miskin kesulitan akses karena untuk itu mereka akan dibebankan biaya tambahan untuk membangun jaringan distribusi tegangan rendah untuk membuat listrik dapat mencapai lokasi tempat tinggal mereka, yang besarnya mencapai ratusan juta rupiah. PLN beralasan dana yang dimiliki terbatas karena TDL dan subsidi hanya menutupi biaya operasional.
Pengalaman Afsel mengajarkan kebijakan listrik gratis adalah sebuah kebijakan politik yang tidak berdiri sendiri. Free Basic Electricity hanya salah satu bagian dari program intensifikasi elektrifikasi nasional yang dicanangkan sejak akhir 1990-an oleh pemerintah pasca-era apartheid. Selain memberikan listrik gratis bagi masyarakat yang benar-benar miskin, Afsel juga memiliki program jangka panjang untuk memberikan listrik bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat yang jauh dari jaringan listrik konvensional melalui subsidi kepemilikan pembangkit listrik tenaga surya, serta berbagai insentif biaya modal pembangunan pembangkit listrik di pedesaan berbasis energi setempat.
Tantangan dari Dahlan Iskan perlu ditanggapi serius oleh eksekutif dan legislatif karena program listrik gratis untuk orang miskin yang berdasarkan pada tantangan tersebut berpotensi menciptakan distorsi, diskriminasi, dan ketidakadilan bagi masyarakat miskin yang sebenarnya dan mereka belum memperoleh akses tenaga listrik, serta mendorong terjadinya moral hazard dan perilaku boros. Untuk menghindari ini, perlu program komprehensif, jangka panjang, dan tepat sasaran. Agar tidak menimbulkan distorsi pada definisi orang miskin dan untuk mencegah ketidakadilan, sasaran kebijakan ini jika dibuat harus dapat menjangkau masyarakat miskin yang belum mendapatkan listrik.
Dalam jangka pendek, program ini bisa dimulai dengan pemberian bebas biaya sambungan bagi kelompok miskin serta ekstensifikasi jaringan. Perlu Rp 8 triliun-Rp 11 triliun untuk sambungan listrik gratis bagi RT miskin. Selanjutnya perlu alokasi dana untuk program listrik pedesaan berbasis energi setempat dan terbarukan.
Perhitungan Bank Dunia (2005), program ini perlu Rp 6 triliun-Rp 8 triliun per tahun, belum termasuk biaya pertambahan kebutuhan tenaga listrik dengan membangun pembangkit konvensional dan perluasan jaringan transmisi dan distribusi.
Di tengah keterbatasan dan kompetisi alokasi anggaran, pendekatan rasional untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mulai melakukan rasionalisasi TDL dan restrukturisasi subsidi listrik.
Fabby Tumiwa Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Sebuah LSM di Jakarta, Pengamat Energi dan Kelistrikan
Tulisan ini telah dikutip dan diambil oleh berbagai blog dan media online lainnya salah satunya: http://www.dpp-pkb.or.id.