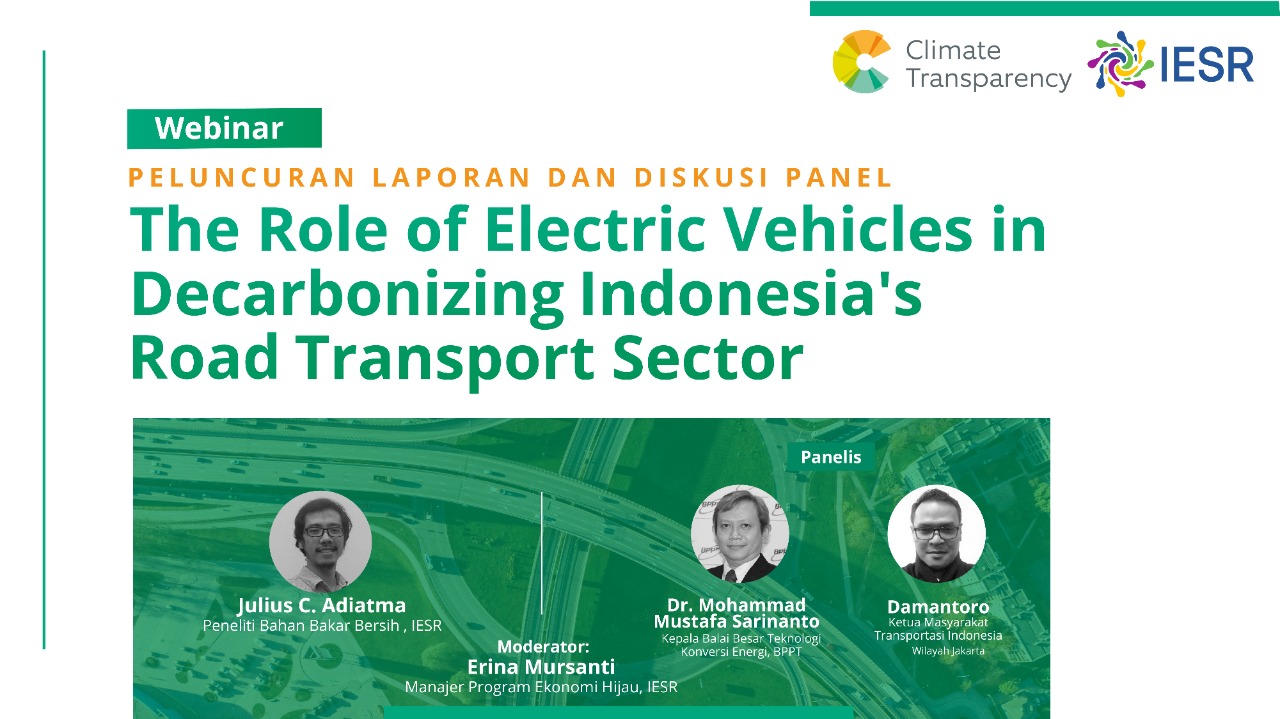Jakarta -- 8 Juli, 2020, IESR. Institute for Essential Services Reform menyambut baik dan mendukung rencana kerjasama Kementerian ESDM bersama dengan International Energy Agency (IEA) dalam sebuah proyek baru tentang ketenagalistrikan dan energi terbarukan. Rencana peluncuran kerjasama ini secara resmi diumumkan oleh IEA, yang dirilis melalui laman resminya pada hari Selasa lalu, 7 Juli 2020. Peluncuran proyek ini dilakukan menjelang KTT Transisi Energi Bersih IEA pada Selasa 9 Juli yang akan mempertemukan sekitar 40 menteri dan tokoh - tokoh penting dari negara-negara yang mewakili sekitar 80% dari permintaan energi global.
IESR menilai kerja sama ini sangat relevan dengan situasi dunia dan situasi Indonesia yang sedang melakukan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dan pada saat yang bersamaan menghadapi tantangan untuk memulihkan investasi di sektor energi, khususnya energi terbarukan untuk mencapai target 23% bauran energi pada 2025.
Read More