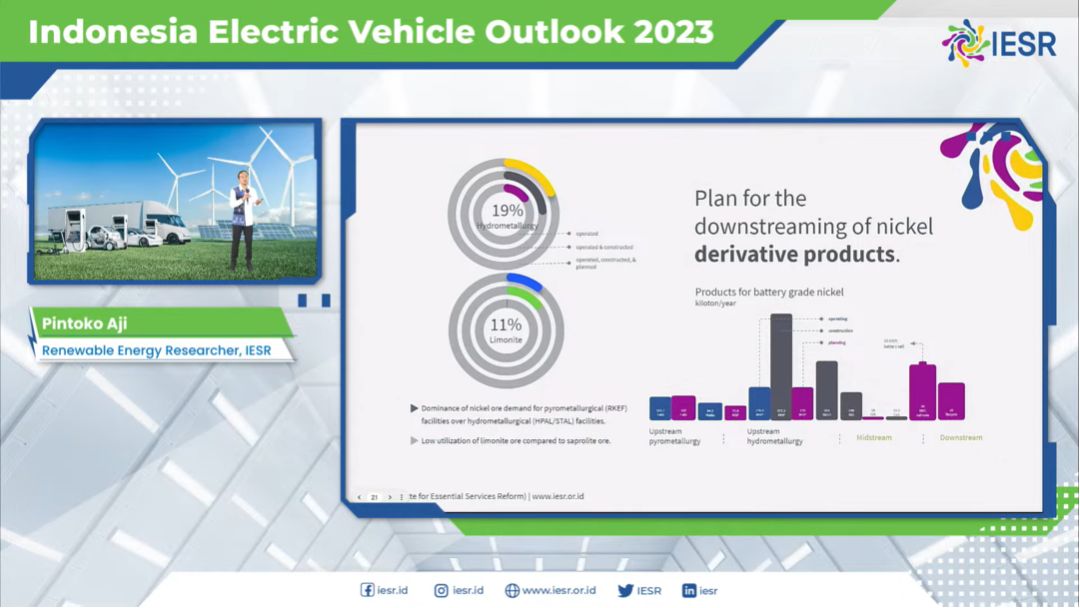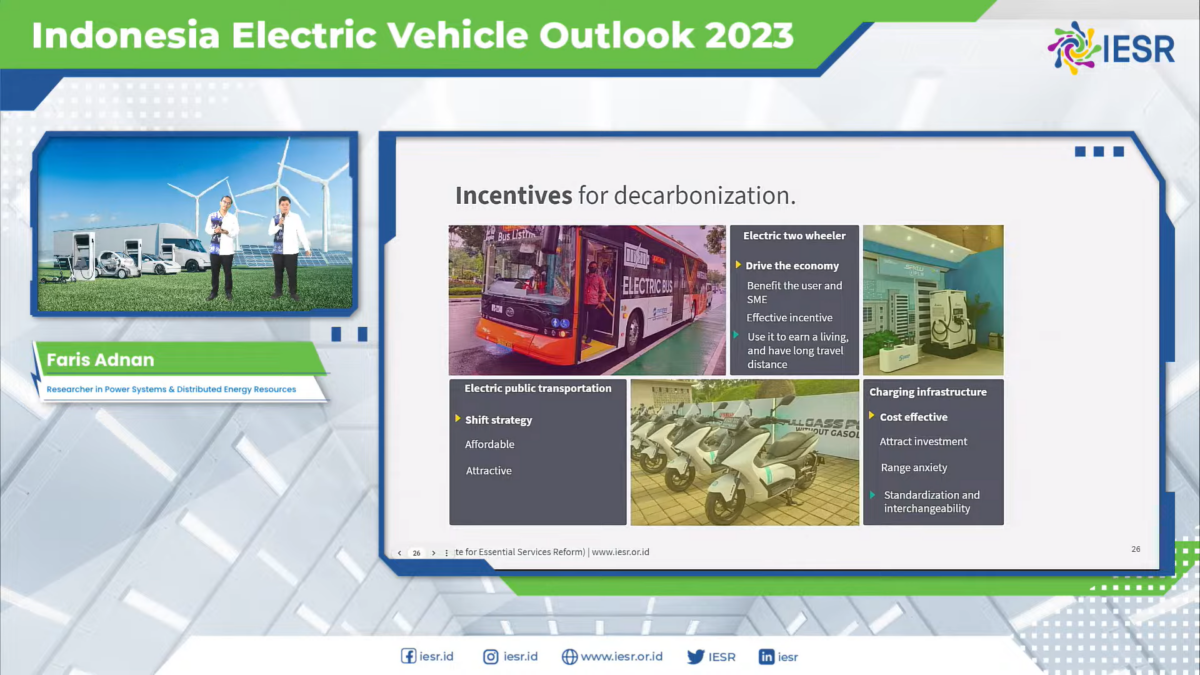Over the present decade, the popularity of electric vehicles (EVs) has witnessed a significant increase with year-over-year sales showing exponential growth. According to reports from Bloomberg New Energy Finance (BNEF), there are already almost 20 million EVs on the road until the end of 2021. To enhance energy efficiency, ensure tailpipe emission reduction, and decrease…