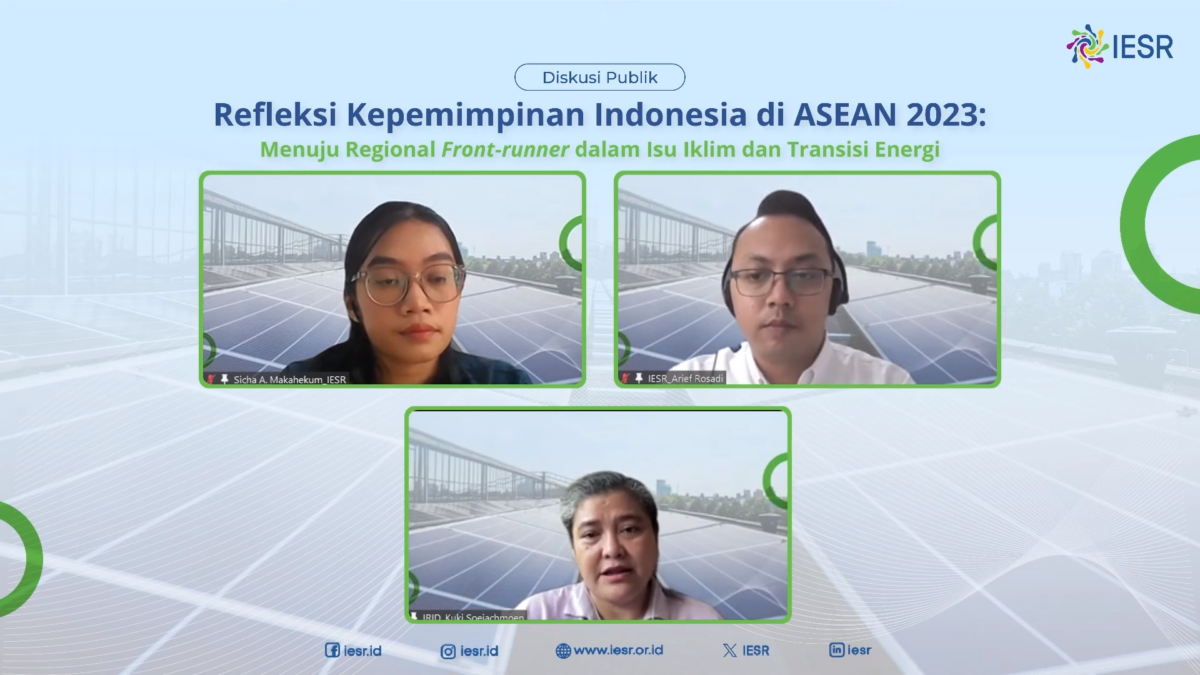Jakarta, 26 Oktober 2023 - Transisi energi yang sedang digaungkan saat ini akan berpengaruh signifikan pada penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara. Berbagai negara telah berkomitmen untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai salah satu aksi kunci transisi energinya. Hal ini perlu diwaspadai oleh negara-negara penghasil fosil seperti Indonesia, karena akan ada penurunan permintaan dari…