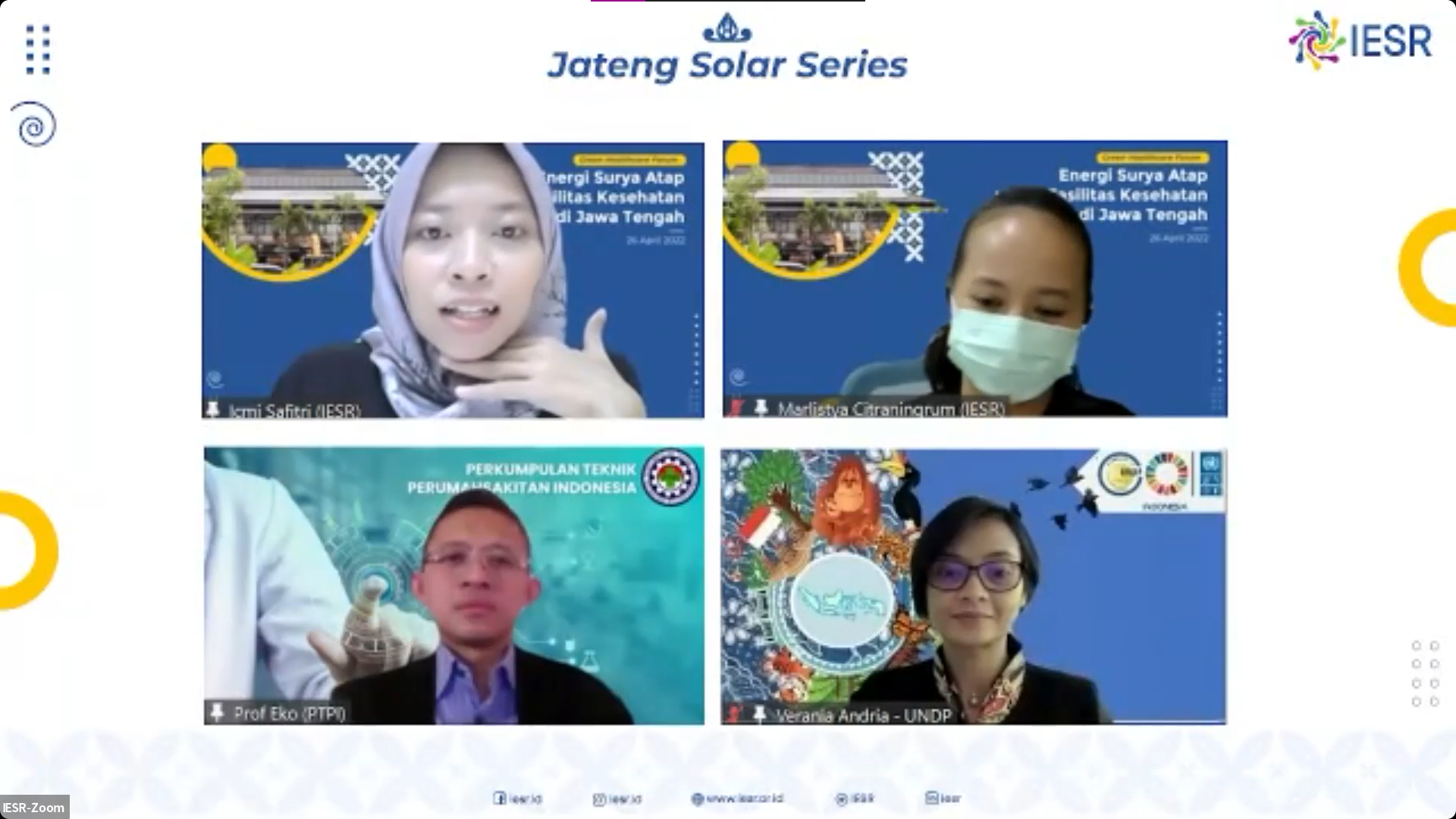Bali, 29 Agustus 2022 - Sektor kelistrikan merupakan salah satu penghasil emisi terbesar setelah sektor kehutanan dan tata guna lahan. Dengan semakin terbatasnya peluang untuk menjaga suhu global pada level 1,5 derajat, dorongan untuk mendekarbonisasi sektor kelistrikan menjadi semakin penting. Perusahaan utilitas listrik akan menjadi pendorong utama upaya dekarbonisasi untuk mencapai emisi nol bersih.
Philippe…