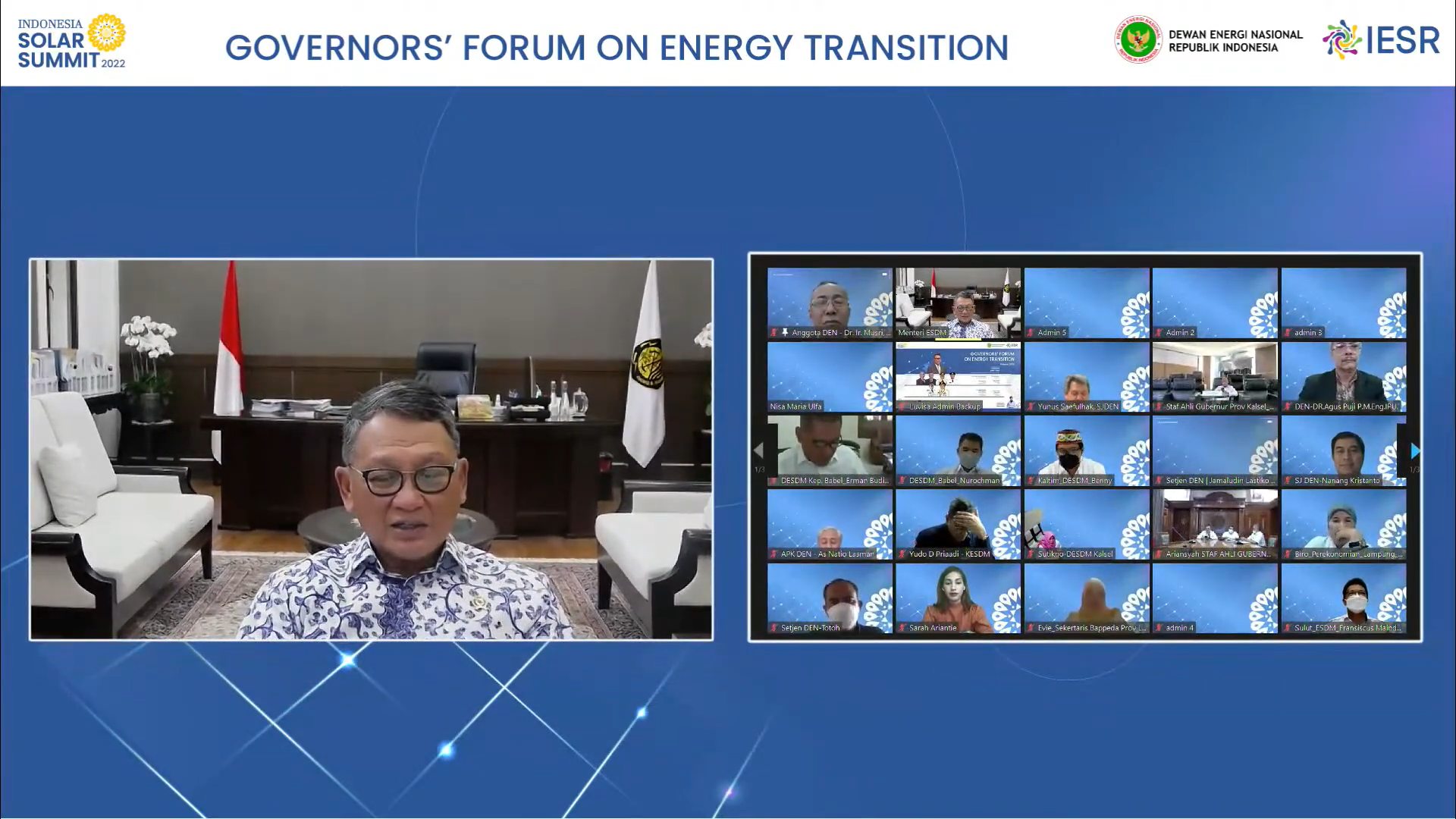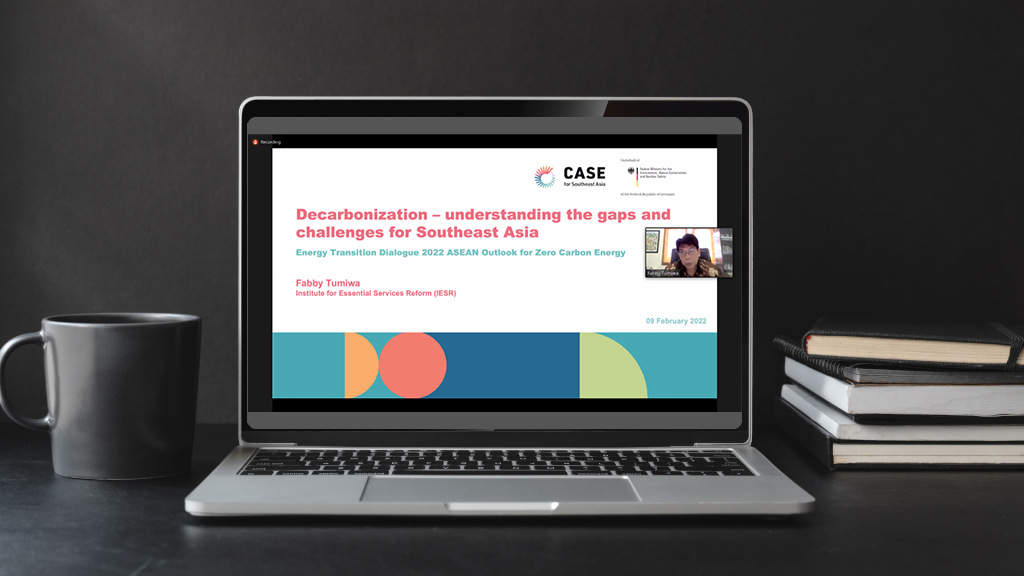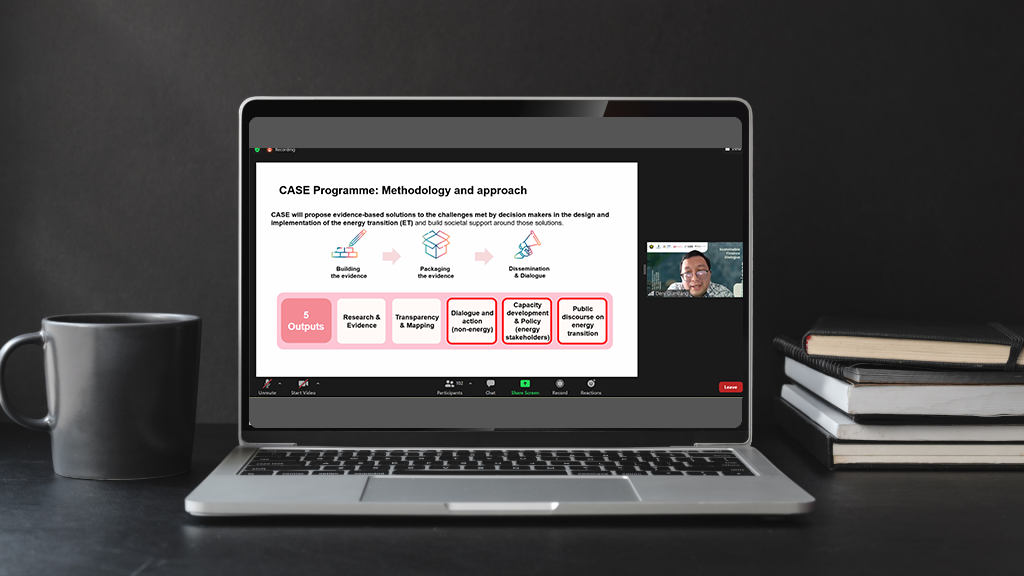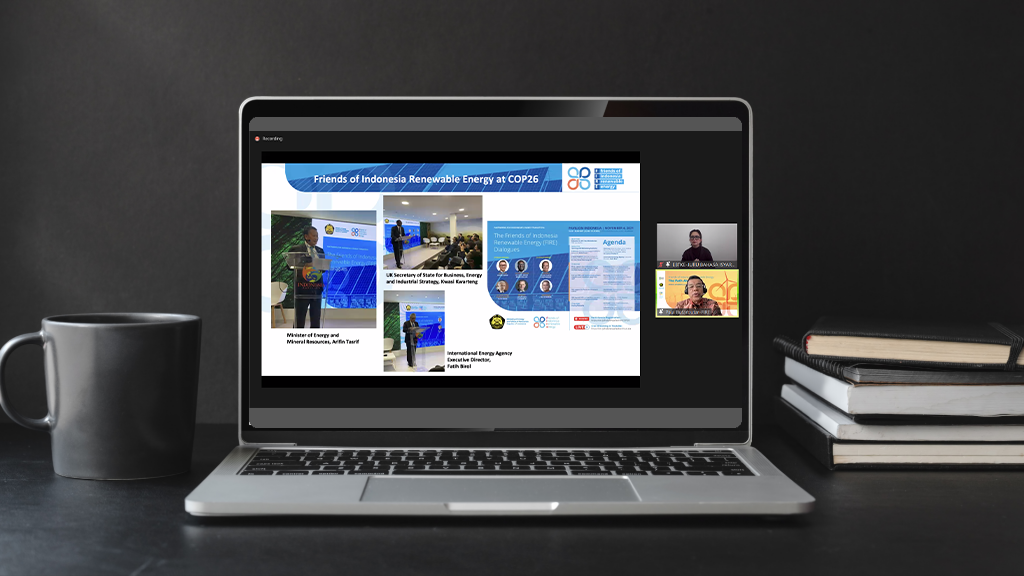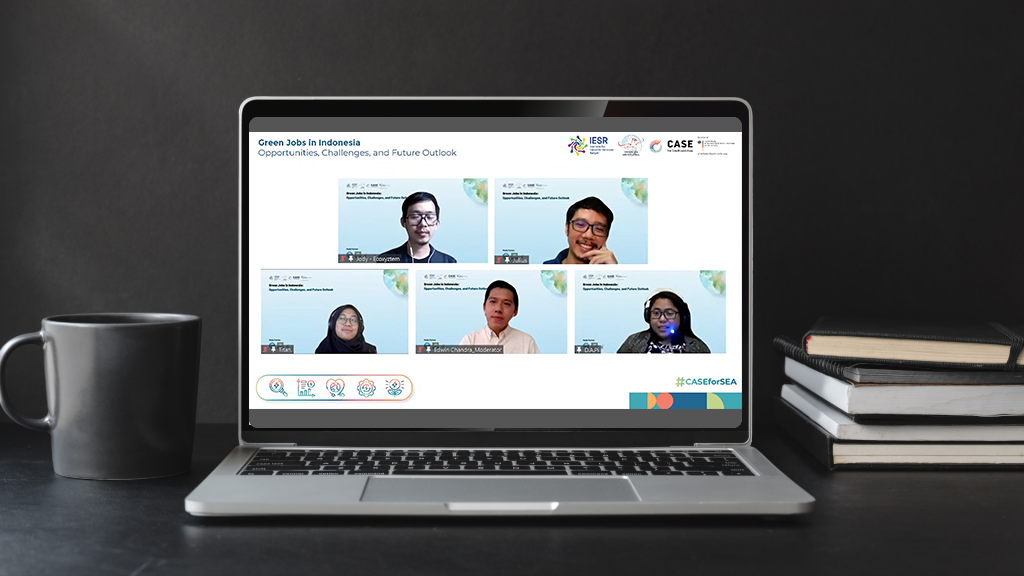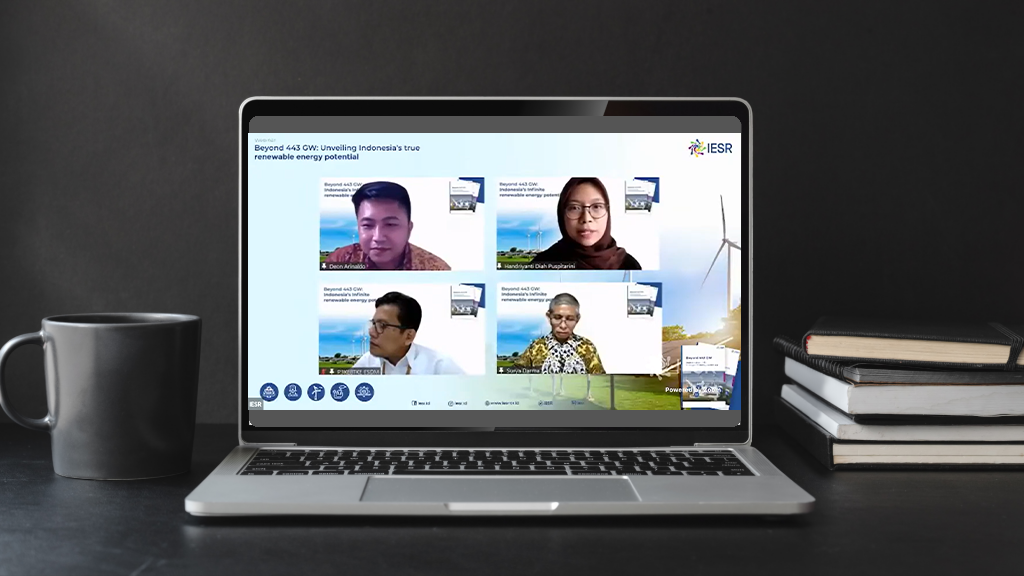Jakarta, 9 Maret 2022 - Kementerian ESDM mencatat adanya peningkatan sebesar 217 MW pada pertengahan tahun 2021. Hal ini membuat total kapasitas pembangkit energi terbarukan pada September 2021 sebesar 10.807 MW. Secara nasional, bauran energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil mencapai 85%. Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mempercepat penetrasi energi terbarukan pada bauran energi salah…