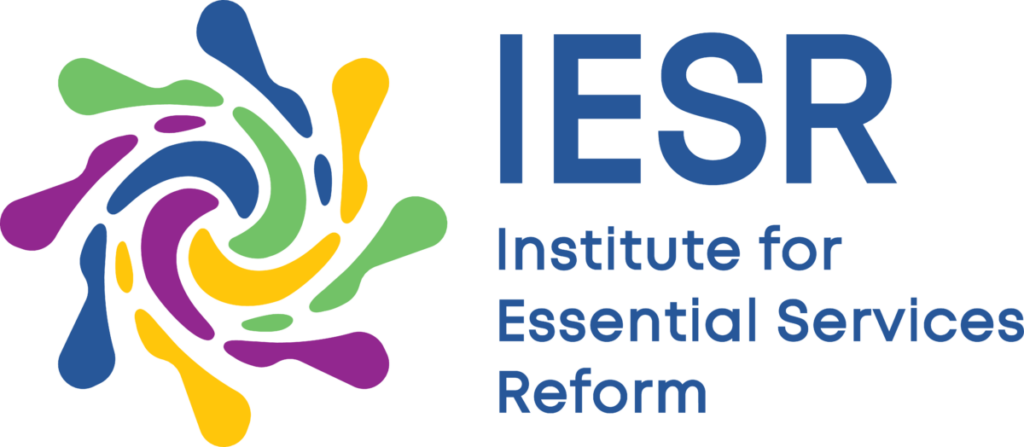Latar Belakang
Menanggapi konsensus global berdasarkan Perjanjian Paris, Indonesia telah berjanji untuk mencapai emisi gas rumah kaca (GRK) nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat, sebagaimana diartikulasikan dalam Kontribusi Nasional yang Ditingkatkan1 dan Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Iklim dan Karbon Rendah (LTS-LCCR) 20502. Kerangka kerja ini menguraikan proses dekarbonisasi bertahap di semua sektor utama, terutama energi dan industri, yang didukung oleh kesiapan dan daya saing pasar serta kebijakan yang mendukungnya.
Menurut NDC1 Indonesia yang Ditingkatkan, negara ini menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89% tanpa syarat dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa (BAU). Sektor industri memainkan peran kunci dalam mencapai target ini, karena menyumbang sekitar 22% dari emisi terkait energi nasional pada tahun 2021, dengan emisi yang diproyeksikan akan tumbuh secara signifikan tanpa intervensi.
Jalan menuju dekarbonisasi industri melibatkan penerapan teknologi rendah karbon, peningkatan efisiensi energi, dan pengintegrasian sumber energi terbarukan. Transisi ini khususnya menantang bagi sektor-sektor yang sulit dikurangi seperti besi dan baja, semen, pupuk, pulp dan kertas, serta tekstil, yang termasuk di antara penghasil emisi industri teratas dan merupakan fondasi bagi perekonomian Indonesia. Industri-industri ini menghadapi hambatan teknologi dan finansial yang melekat untuk melakukan dekarbonisasi yang cepat, namun mereka harus beradaptasi agar tetap kompetitif dan patuh terhadap norma-norma global yang muncul.
Di antara pendorong dasar untuk transisi ini adalah pengembangan ekosistem pasar hijau, khususnya melalui pengadaan publik hijau (GPP), instrumen kebijakan penting untuk merangsang permintaan barang dan jasa rendah emisi dan untuk mempercepat dekarbonisasi dalam industri. GPP telah digunakan secara global untuk mempercepat transformasi industri, seperti yang terlihat di Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan 3,4. Saat ini, kesiapan regulasi dan kelembagaan Indonesia untuk pengadaan publik hijau masih terbatas. Sementara Peraturan Presiden No. 16/2018 tentang Pengadaan Umum memberikan panduan umum tentang pengadaan yang ramah lingkungan, implementasinya masih dalam tahap awal.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah memperkenalkan upaya percontohan dan pedoman untuk produk ramah lingkungan, tetapi adopsi arus utama di seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) masih minim5. Banyak produk ramah lingkungan, seperti peralatan hemat energi, bahan bangunan rendah karbon, atau input berkelanjutan yang bersertifikat, belum diprioritaskan dalam keputusan pengadaan karena kurangnya insentif, preferensi harga, spesifikasi teknis, atau sistem sertifikasi yang dapat diverifikasi. Hal ini membatasi kemampuan GPP untuk memberi sinyal permintaan dan merangsang investasi rendah karbon di seluruh industri. Dan tanpa dukungan yang ditargetkan dan insentif yang jelas, banyak perusahaan menunda adopsi teknologi rendah karbon yang dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan di pasar global yang semakin dibentuk oleh standar karbon dan kebijakan perdagangan hijau (misalnya, CBAM UE)6.
Secara paralel, dampak ekonomi dari dekarbonisasi industri terhadap daya saing nasional masih belum cukup dipahami. Lebih jauh, penting untuk mengeksplorasi bagaimana dekarbonisasi sektor industri Indonesia dapat berkontribusi pada daya saing ekonomi globalnya. Indeks Daya Saing Global (GCI), yang dikembangkan oleh Forum Ekonomi Dunia, mengevaluasi produktivitas ekonomi jangka panjang suatu negara melalui metrik seperti infrastruktur energi, regulasi lingkungan, kapasitas inovasi, dan stabilitas ekonomi makro7. Pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat ke-50 dari 141 negara. Namun, masih belum dieksplorasi bagaimana dekarbonisasi industri dapat memengaruhi indikator utama seperti pertumbuhan PDB, akses listrik, adopsi teknologi bersih, dan ekosistem inovasi yang secara langsung memengaruhi peringkat GCI Indonesia.
Pada saat yang sama, industri enggan berinvestasi dalam teknologi hijau karena dianggap biaya tinggi dan keuntungan yang tidak pasti. Untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan ini, penggunaan Analisis Biaya-Manfaat (CBA) menjadi alat penting untuk mendukung adopsi teknologi. Dengan mengukur trade-off ekonomi dan lingkungan, CBA memungkinkan industri dan pembuat kebijakan untuk:
- Mengidentifikasi teknologi dekarbonisasi yang hemat biaya;
- Membandingkan biaya jangka pendek dengan keuntungan efisiensi jangka panjang, mitigasi risiko, dan manfaat daya saing;
CBA juga memainkan peran strategis dalam menyelaraskan kesiapan industri sisi penawaran dengan sinyal pasar sisi permintaan. Misalnya, jika proses pengadaan publik mulai membutuhkan bahan konstruksi rendah karbon atau input berkelanjutan yang bersertifikat, industri perlu memahami dengan jelas alasan ekonomi dan keunggulan kompetitif dalam memenuhi persyaratan tersebut
Pada akhirnya, studi ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa dekarbonisasi industri bukanlah hambatan bagi kinerja bisnis atau pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hal itu dapat membuka peluang pasar baru, khususnya di segmen produk hijau dan memperkuat posisi global Indonesia sebagai ekonomi yang kompetitif dan tangguh terhadap iklim. Dengan menganalisis hubungan antara kesiapan kebijakan, daya saing ekonomi, dan investasi teknologi melalui perangkat seperti pembandingan GCI, pemodelan investasi, dan CBA, studi ini akan menawarkan wawasan praktis bagi pemerintah dan industri. Studi ini juga akan membantu mengidentifikasi segmen industri hijau yang dapat ditingkatkan skalanya oleh Indonesia berdasarkan keunggulan sumber daya domestik dan tren permintaan global seperti bahan konstruksi berkelanjutan, teknologi hemat energi, atau input manufaktur rendah karbon.
Seluruh dokumen yang dipersyaratkan dapat diunduh melalui tautan ini (StatementLetterConsultant) dan proposal diharapkan diterima paling lambat pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat (WIB, GMT+0700) pada hari Rabu, 11 Juni 2025, dan ditujukan kepada faricha@iesr.or.id (Industrial Decarbonization Coordinator for Technology and Policy, IESR) dengan cc ke: juniko@iesr.or.id (Industrial Decarbonization Manager IESR). Mohon cantumkan “RFP Response – Economic Impact Analysis of Industrial Decarbonization in Indonesia” pada subject email. Seluruh proposal harus diajukan oleh organisasi resmi atau perwakilan yang ditunjuk oleh organisasi tersebut.