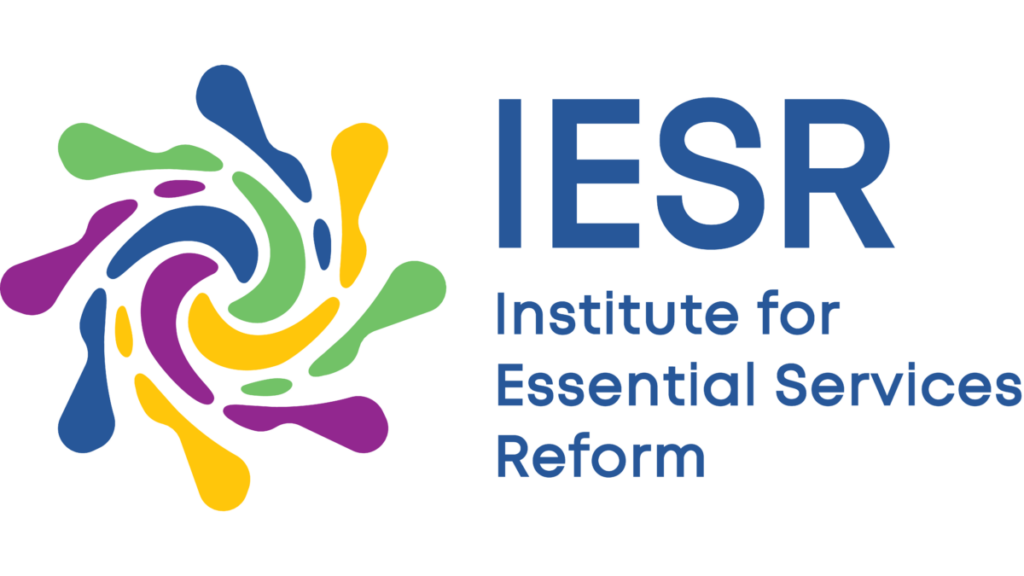Latar Belakang
Sektor industri memiliki peran krusial dalam mendorong perekonomian Indonesia dan merupakan segmen konsumen energi yang signifikan. Menurut studi IEA tahun 2020, sekitar 37% dari total konsumsi energi negara ini berasal dari sektor industri. Namun, karena ketergantungan Indonesia yang tinggi pada bahan bakar fosil, sektor industri muncul sebagai sumber utama polusi di negara ini. Situasi ini membahayakan lingkungan dan membuat sektor ini rentan terhadap fluktuasi pasar energi global yang tidak terduga. Akibatnya, penerapan dekarbonisasi memberikan tiga keuntungan sekaligus – membantu mengurangi emisi karbon, memenuhi persyaratan & permintaan pasar yang ketat, dan sekaligus memperkuat ketahanan energi.
Ada delapan industri yang berkontribusi tinggi terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) secara keseluruhan. Industri-industri ini adalah semen, keramik dan kaca, kimia, pupuk, makanan dan minuman, besi dan baja, pulp dan kertas, serta tekstil. Industri-industri ini secara kolektif bertanggung jawab atas sekitar 56% dari total emisi GRK di sektor industri pada tahun 2016 (CMEA, 2018). Menurut temuan studi IESR, konsumsi energi berkontribusi lebih dari 68% dari total emisi GRK industri pada tahun 2017.
Meskipun para pemangku kepentingan di Indonesia telah membuat kemajuan dan komitmen yang signifikan terhadap dekarbonisasi sektor industri, hal ini belumlah memadai. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sepakat untuk menargetkan tambahan energi terbarukan sebesar 42,6 GW, atau sekitar 61% dari total kapasitas tambahan yang direncanakan (RUPTL 2025-2034). Target ini relatif rendah dibandingkan negara-negara lain yang telah menjanjikan jaringan listrik bersih pada tahun 2030-an dan 2040-an. Meskipun demikian, hal ini tetap akan menguntungkan upaya dekarbonisasi industri, terutama bagi para pelaku industri yang mengandalkan sumber daya on-grid, jika rencana tersebut diimplementasikan dengan baik.
Sebaliknya, banyak industri di Indonesia masih intensif menggunakan dan terus membangun pembangkit listrik off-grid, alias captive. Pada tahun 2023, 13-14 GW atau 60% dari total kapasitas pembangkit listrik mandiri saat ini adalah pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU). Nilai ini diperkirakan akan tumbuh hingga tahun 2030, dengan tambahan kapasitas PLTU mandiri sekitar 20 GW. Selain itu, terdapat pula pembangkit listrik tenaga LNG dan gas alam yang substansial, baik yang sudah beroperasi maupun yang sedang dalam tahap pembangunan. Hal ini menyoroti urgensi dekarbonisasi sektor industri, termasuk PLTU mandiri berbahan bakar fosil.
Langkah penting dalam substitusi pasokan listrik berbahan bakar fosil, baik dari jaringan listrik maupun pembangkit mandiri, adalah memutuskan pasokan mana, kapan, dan bagaimana pasokan tersebut akan digantikan, serta sumber energi terbarukan apa yang layak sebagai penggantinya, baik dari sudut pandang teknis, ekonomi, maupun hukum. Keputusan ini harus didasarkan pada fakta, data, dan analisis yang cermat di tingkat perusahaan untuk menentukan jalur yang paling menguntungkan, termasuk menetapkan baseline dan target, menghitung biaya dan manfaatnya, serta langkah-langkah pengadaan untuk setiap operator aset tersebut. Lebih lanjut, membangun portofolio yang kokoh dan menyiapkan rencana komunikasi serta klaim yang kuat atas langkah-langkah pengadaan energi terbarukan ini dapat terbukti bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan pasar tertentu sekaligus menarik minat investor.
Clean Energy Buyers Institute (CEBI) berkolaborasi dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam mengadaptasi dan memberikan peningkatan kapasitas berkualitas terkait pengadaan energi terbarukan melalui Renewable Energy Procurement Academy, atau disingkat akademi, di Indonesia. Kegiatan Akademi ini meliputi pemberian pelatihan tatap muka kepada perwakilan pelaku industri strategis untuk membimbing mereka secara langsung dalam memahami pentingnya dan langkah-langkah dalam pengadaan energi terbarukan.
Timeline Proposal
Calon penyedia jasa harus menyerahkan paket proposal yang terdiri dari proposal teknis (latar belakang, tugas yang akan dilaksanakan, metodologi, jadwal), proposal biaya (total tarif tenaga kerja yang diusulkan dan biaya lainnya), serta resume & portfolio yang relevan. Pengajuan proposal dibuka hingga 07 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB, ditujukan kepada Program Manager Energy System Transformation di deon@iesr.or.id dan cc ke falah@iesr.or.id, dan auzora@iesr.or.id . Mohon tuliskan “RFP Response – Proposal – EO Training CEBI – [Organization Name]” pada kolom subjek proposal. Semua proposal harus ditandatangani oleh organisasi resmi atau perwakilan organisasi yang mengajukan proposal.