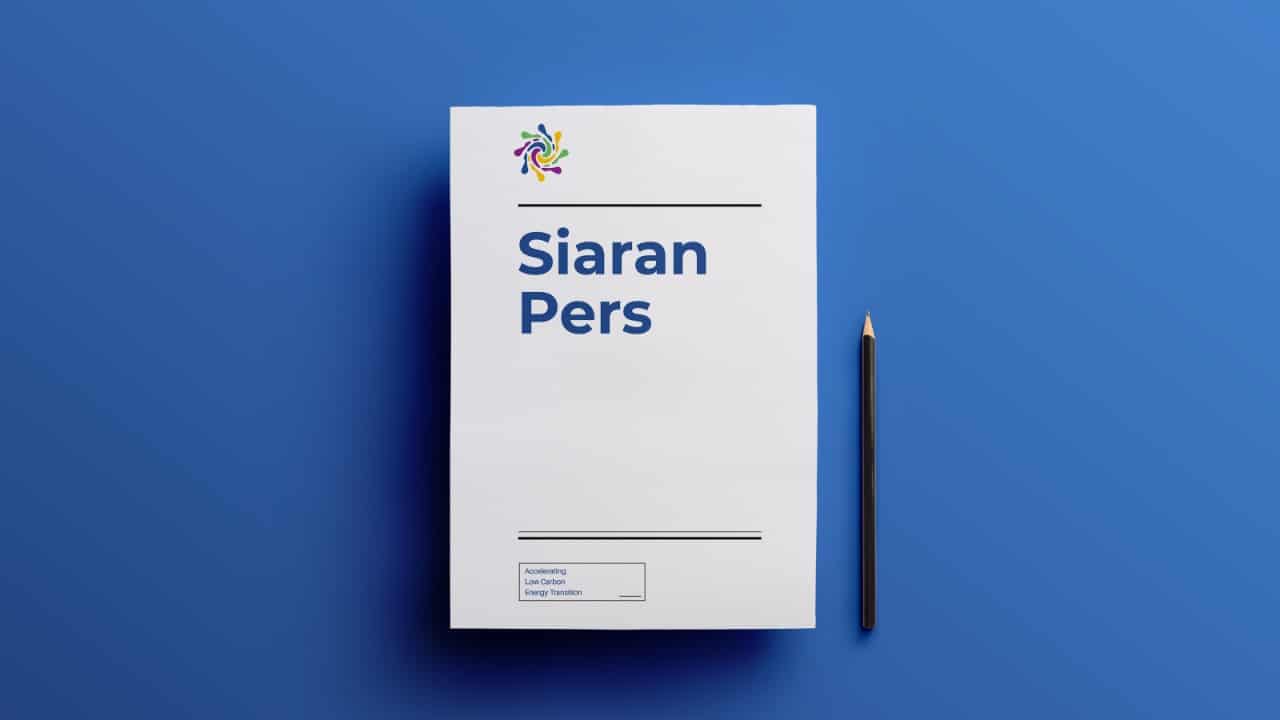Jakarta, 13 Oktober 2025 - Transisi energi berkeadilan dan inklusif di Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa transformasi menuju sumber energi bersih tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama yang rentan. Dengan menggali potensi energi terbarukan yang melimpah, seperti tenaga surya, angin, dan geotermal, Indonesia memiliki peluang…