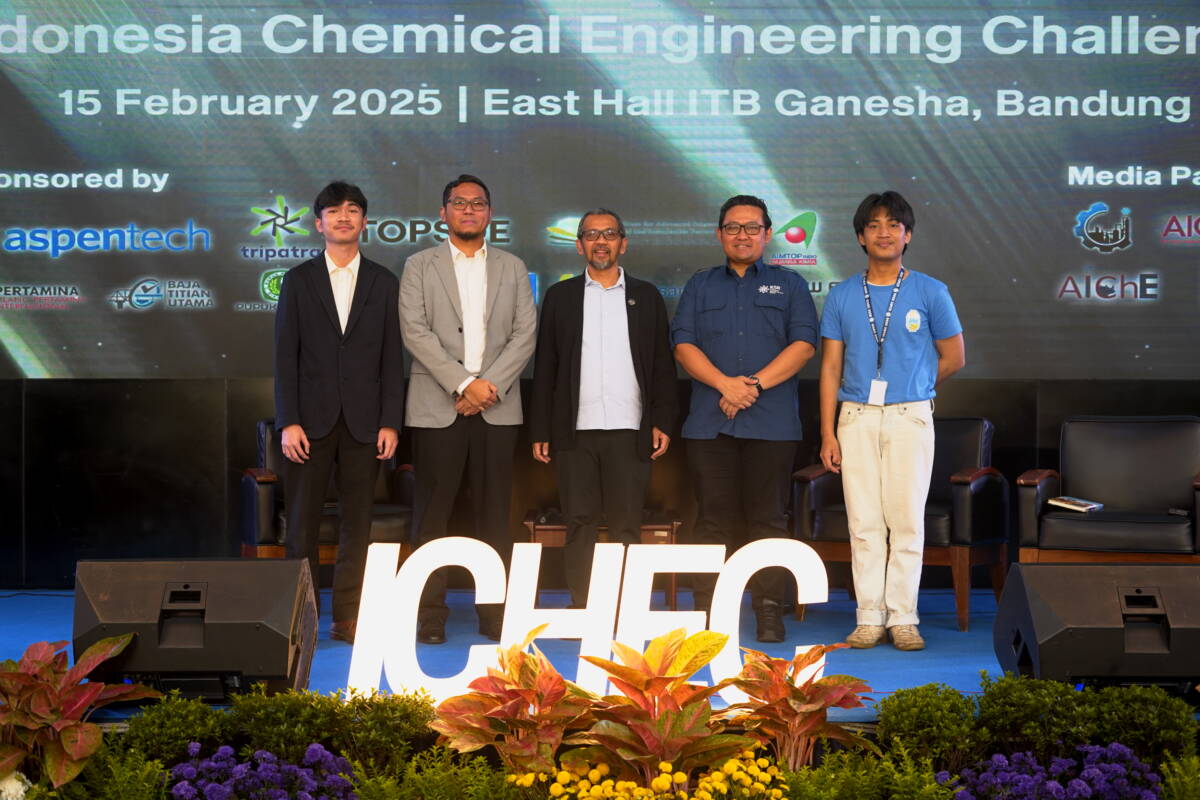Jakarta, 20 Februari 2026 – Transisi energi seringkali dipersepsikan sebagai agenda mahal yang membebani ekonomi. Padahal, menurut Staf Mobilitas Berkelanjutan, Lingkungan Bersih, dan Bangunan IESR, Reananda Hidayat, anggapan tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan terbaru. Menurutnya, teknologi energi terbarukan hari ini justru sudah menjadi pilihan paling ekonomis.
“Banyak yang masih berpikir bahwa energi terbarukan terlalu mahal dan tidak kompetitif dibandingkan energi fosil. Padahal, dalam satu dekade terakhir, biaya pembangkitan listrik dari energi surya dan angin turun sangat signifikan,” tegas Reananda dalam acara seminar Indonesia Chemical Engineering Challenge (IChEC) 2026 pada Minggu (15/2).
Mengutip data dari International Renewable Energy Agency (IRENA), kata Rean, pembangkit listrik tenaga angin darat kini menjadi sumber listrik baru termurah secara global, dengan rata-rata levelized cost of electricity (LCOE) sekitar USD 0,034 per kWh. Disusul oleh surya fotovoltaik (PV) sebesar USD 0,043 per kWh dan tenaga air sebesar USD 0,057 per kWh. Angka ini membuktikan bahwa transisi energi bukan lagi soal idealisme lingkungan, melainkan keputusan ekonomi yang rasional dan berbasis data.
“Dengan perkembangan teknologi yang semakin ekonomis, perubahan cara pandang perlu dilakukan pemangku kepentingan. Misalnya saja perencanaan sistem ketenagalistrikan di Inggris saat melakukan penghentian bertahap pembangkit batu bara dan ekspansi energi terbarukan melalui kerangka National Grid ESO. Pada awalnya, sistem listrik lebih banyak dirancang berdasarkan biaya pembangkitan jangka pendek yang terendah, sehingga pembangkit batu bara dan gas tetap dipertahankan karena infrastrukturnya sudah tersedia,” tegas Rean.
Namun, ketika pendekatan optimasi multi-objektif mulai diterapkan yang tidak hanya mempertimbangkan biaya, tetapi juga emisi karbon, volatilitas harga bahan bakar, keandalan sistem, dan risiko jangka panjang, hasilnya berubah drastis. Model tersebut menunjukkan bahwa meskipun angin dan surya membutuhkan investasi awal lebih besar, biaya bahan bakarnya nol dan emisinya sangat rendah, sehingga secara sistemik lebih murah dalam jangka panjang.
“Ketika harga karbon dan ketidakpastian harga bahan bakar dimasukkan dalam perhitungan, batu bara menjadi tidak lagi menarik secara ekonomi. Hasilnya, dalam waktu sekitar satu dekade, porsi listrik dari batu bara di Inggris turun dari sekitar 40 persen pada 2012 menjadi hampir nol. Keputusan tersebut bukan semata dorongan lingkungan, tetapi hasil pemodelan terpadu yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi, pengurangan emisi, dan keandalan sistem,” papar Rean.
Rean mengatakan, berkaca dari pengalaman tersebut, terdapat pelajaran penting bagi Indonesia. Seperti konsistensi kebijakan adalah kunci. Pertumbuhan industri manufaktur surya di Tiongkok menunjukkan bahwa target jangka panjang yang jelas, insentif yang terukur, dan kepastian regulasi mampu membangun kepercayaan investor dan mempercepat skala industri. Negara yang bergerak lebih awal dalam rantai pasok energi terbarukan dan kendaraan listrik berhasil mengamankan pangsa pasar global.
“Bagi Indonesia, dengan cadangan nikel yang besar, peluangnya bukan hanya sebagai eksportir bahan mentah. Nilai tambah dapat diciptakan melalui hilirisasi, produksi baterai, hingga peningkatan kapasitas teknologi. Namun, transisi ini juga harus dikelola secara sosial. Pengalaman Eropa dalam mempensiunkan tambang batu bara menunjukkan bahwa tanpa program pelatihan ulang dan diversifikasi ekonomi daerah, pekerja dan komunitas lokal berisiko tertinggal. Pendekatan “just transition” menjadi syarat penting agar transformasi industri tetap stabil secara politik dan sosial,” kata Rean.