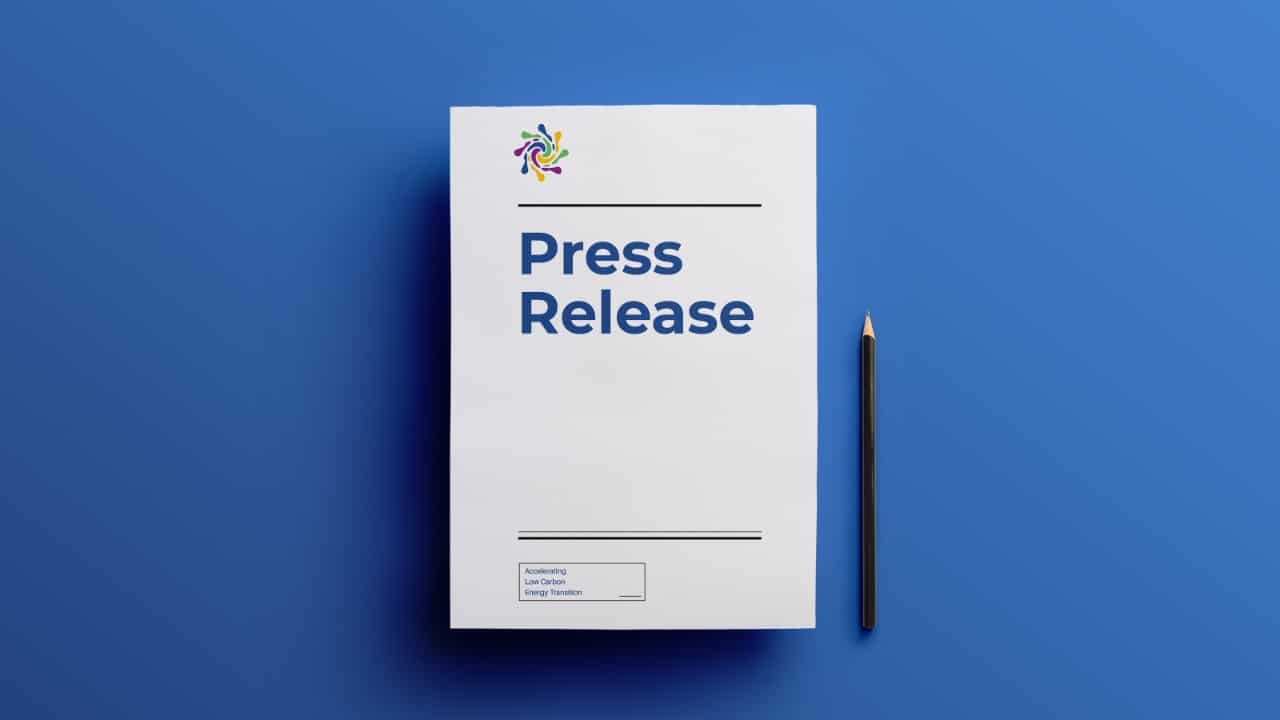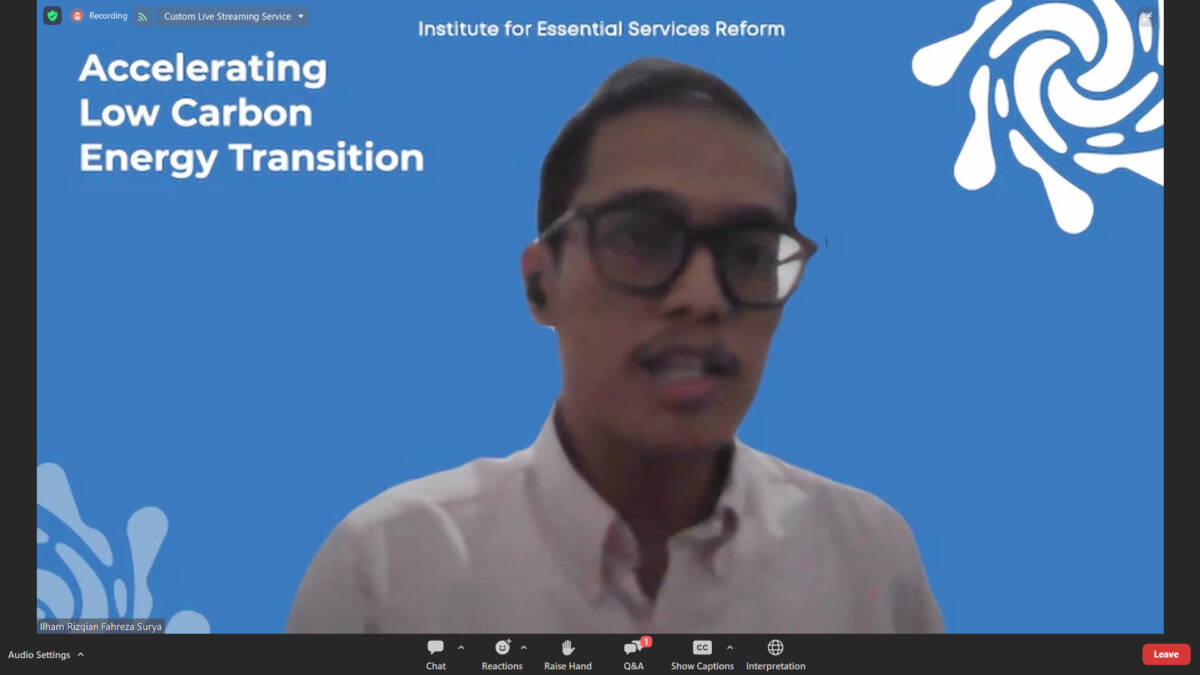Jakarta, 30 April 2024 - Transformasi energi memerlukan pembiayaan yang memadai untuk memastikan prosesnya berjalan lancar dan adil. Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank terkemuka di bidang transisi energi dan lingkungan berbasis di Jakarta melakukan diseminasi laporan berjudul “ Identifikasi Kebutuhan Pembiayaan untuk Transformasi Sektor Ketenagalistrikan Indonesia yang Berkeadilan” .…