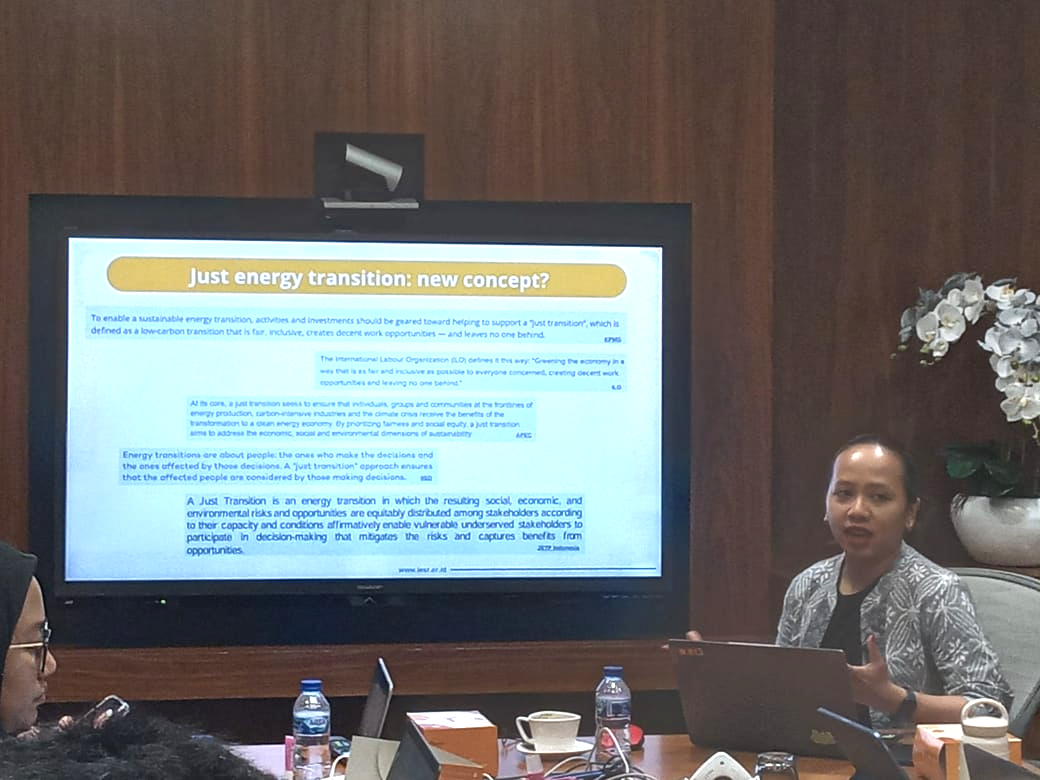Jakarta, 6 November 2024 - Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) merangkumkan hasil diskusi dalam Indonesia Energy Transition Forum (IETD) 2024 menjadi rekomendasi percepatan transisi energi berkeadilan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. ICEF dan IESR menekankan bahwa transisi energi merupakan cara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi…