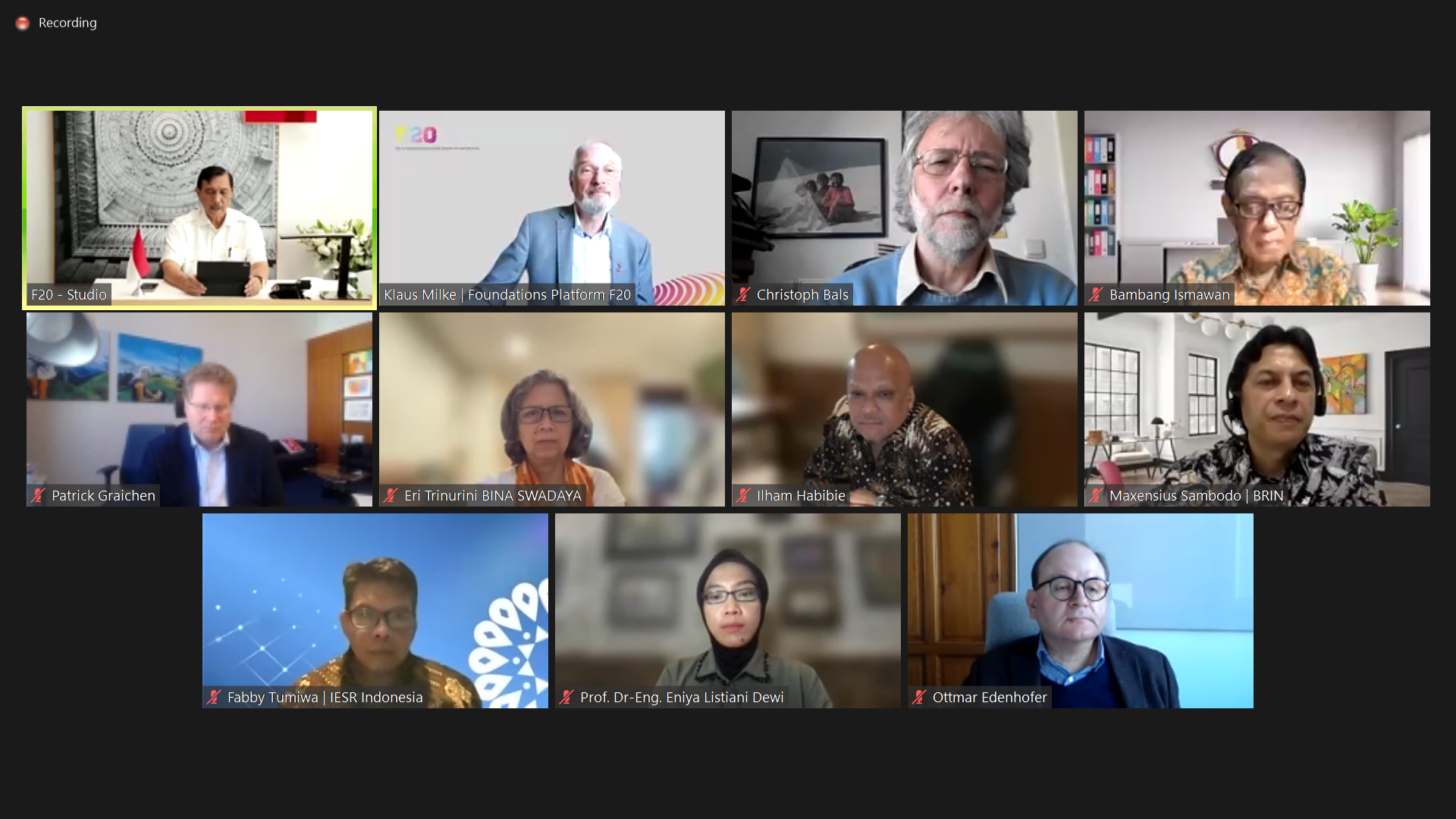Jakarta, 27 Mei 2025 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) baru saja mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 pada Senin (26/5). RUPTL terbaru ini menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik energi baru dan energi terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW (61%) dan 10,3 GW (15%) penyimpanan daya ( storage…