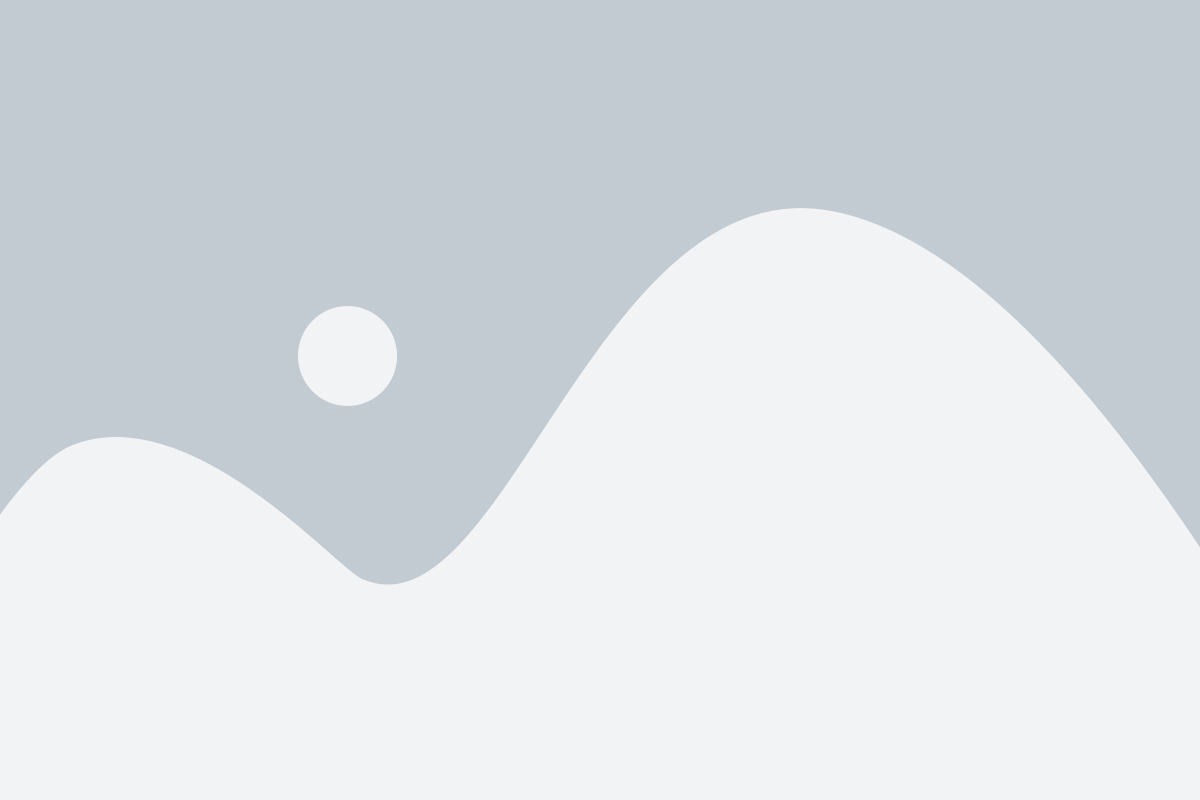Oleh: Musfarayani
Tidak banyak yang tahu bahwa masalah keterbukaan pelaporan pendapatan kegiatan tambang oleh perusahaan tambang dan penerimaan negara atas usaha itu, telah menimbulkan celah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat tinggi. Belum lagi menyebut dampak ekologisnya bagi alam dan berbagai konflik horizontal yang telah menimbulkan masalah sosial, politik dan ekonomi bagi masyarakat asli yang lahan dan hutannya dijadikan areal kegiatan usaha tambang atau dikenal sebagai usaha ektraktif industri.
Hal ini terungkap dalam pertemuan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Social Organization/CSO) Internasional, se-ASEAN yang membahas tentang Inisiatif Keterbukaan Ekstraktif Industri (The Extractive Industry Transparency Imitative (EITI), di Inter Continental, Jakarta (28/2). Acara ini dihadiri CSO dari Timor Leste, Kamboja, Vietnam, Philipina, dan Indonesia sebagai tuan rumah, yang dipandu langsung oleh Oxfam Amerika dan RWI (Revenue Watch Institute). Pertemuan ini sendiri dimaksudkan sebagai persiapan CSO se-ASEAN dalam menghadapi Konfrensi EITI se-Asia yang akan (telah berlangsung) di Shangrila, Indonesia, awal Maret 2010.
Kendati tidak semua CSO sepaham dalam melihat persoalan EI bisa terselesaikan lewat EITI, namun sejumlah CSO sudah mendorong upaya hal ini untuk terus dilakukan seiring dengan berbagai advokasi persoalan EI lainnya. Para CSO juga melihat bahwa ketiadaan tatakelola yang baik dalam hal mengatur keterbukaan usaha EI telah melemahkan tanggungjawab pemerintah yang harusnya secara terbuka memperlihatkan kepada publik pendapatan yang diterima dalam usaha EI ini. Termasuk kekhawatiran semakin tidak terkontrolnya eksplorasi sumber daya alam yang berakibat pada rusaknya ekologis, dan penderitaan rakyatnya.
“Sebagai contoh saja di Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara, produksi batu bara Indonesia adalah terbesar kedua. Ironisnya daerah-daerah yang menghasilkan batu bara ini justru adalah daerah yang dikenal paling miskin dan tertinggal untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan isu aktivitas korupsi yang tinggi, isu lingkungan, HAM dan juga kemiskinan,” jelas Fabby Tumiwa, Executive Director of Institute for Essential Services Reform (IeSR), Indonesia yang mempresentasikan gambaran umum tentang peta masalah EITI di kawasan ASEAN.
Ironis lagi, negara ASEAN yang kaya akan sumber daya alam tambang dan mineralnya seperti Indonesia, Laos, dan Philipina yang pengelolaannya sebagain besar “dikuasai” perusahaan asing seperti Petronas, Chevron dan Pertamina ini justru mendapatkan pendapatan GDP di sektor EI lebih kecil dibandingkan sektor lainnya.
“Sebagai contoh di Indonesia pendapatan dari sumber mineral sangatlah kecil jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Di sektor tambang, bahkan, pemerintah hanya dapat royaltinya saja dan bukan pendapatannya,” jelas Fabby lagi.
CSO Asean menyebut situasi yang disebut Fabby sebagai ”Resource Curse”. Di Philipina misalnya yang dikenal sebagi penghasil mineral metalik (kromit, tembaga, emas, besi dan nikel) nomor satu dunia, juga penghasil bauksit terbesar, hanya mendapatkan kontribusi di sektor ini sebesar 1,1% dan 1,2% (1997 dan 2007) untuk GDP mereka. Saat ini ada 24 proyek tambang yang beroperasi di Philipina (2006).
“Itu hanya 2% dari total eksportnya Philipina,” jelas Lord Byron Abadeza, Koordinator Project Transparency and Accountability Network, Philipina.
Senada juga ditambahkan oleh Ridaya Laodengkowe, Koordinator Koalisi Nasional Publish What You Pay, Indonesia. Dalam kasus di Riau misalnya, provinsi yang dikenal kaya sumber minyak ini, 25% penduduknya justru tidak bisa menyelesaikan Sekolah Dasar.
Fenomena semacam ini menurut peserta CSO Meeting disebabkan sangat minimnya kesadaran perusahaan EI dan pemerintah masing-masing Negara dalam melakukan keterbukaan pelaporan pendapatan dan penerimaan hasil usaha EI. Sehingga rentan akan praktek korupsi, dan keuntungan dari hal itu ternyata memang tidak membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.
Salah satu kasus nyata di Indonesia adalah ketika ICW (Indonesia Corruption Watch), telah menemukan pelanggaran tentang kasus penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan batu bara milik anak perusahaan tokoh politik dan penguasa berpengaruh di Indonesia (media advisory – bisa dilihat di “ICW Ungkap Manipulasi Penjualan Batu Bara Grup Bakrie” diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/02/15/brk,20100215-225895,id.html).
Di antara Negara Asean lainnya, hanya Timor Leste yang memastikan bahwa 80% hasil minyak buminya merupakan pendapatan utama Negara setelah kopi (20%) dengan pertanggungjawaban yang cukup terbuka. Mericio Akara, Direktur dari NGO Luta Hamutuk (semacam ICW-nya Indonesia-red), Timor Leste menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya minyak Timor memang dikelola JPDA (Joint Petroleum Development Area) dengan pembagian yang cukup adil, Timor mendapatkan 90% sementara Australia 10%, termasuk 5% pembayaran royaltinya.
Rentan Konflik
Ketidakterbukaan pertanggungjawaban laporan pendapatan perusahaan EI dan penerimaan yang diperoleh pemerintah ini pula yang dianggap CSO Meeting sebagai salah satu matarantai penting yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah konflik sosial dan ekonomi yang cukup tinggi.
Di Indonesia, dalam catatan Koalisi Nasional Publish What You Pay, Indonesia, konflik vertikal selalu terjadi di wilayah yang dikenal sebagai penghasil EI tertinggi seperti di Papua, Kalimantan dan NAD. Seperti disebut di atas, wilayah ini justru menjadi provinsi yang tertinggal dan miskin di antara provinsi lainnya.
Dalam cerita di Kamboja terungkap berbagai usaha EI di area sekitar Danau Tonle Sap telah menimbulkan berbagai konflik yang cukup tinggi. Area itu kini telah “diramaikan” blok-blok izin usaha berbagai kegiatan EI. Salah satu areanya yang disebut area Blok A dikuasai oleh Chevron.
“Telah banyak di area lahan-lahan di Kamboja semakin menunjukkan peningkatan eksplorasi sumberdaya alam yang semakin meningkat. Kebanyakan perusahaannya adalah dari Barat dan ini juga sarat dengan korupsi,” jelas Chhith Sam Ath, Direktur Ekesekutif dari The NGO Forum on Cambodia, Kamboja.
Ath juga menjelaskan bahwa saat ini ada 20 perusahaan minyak yang telah mendapatkan konsensi dari pemerintah. Emas merupakan pendapatan terbesar dibanding usaha EI lainnya di Kamboja. Kamboja berharap banyak pendapatan atas gas dan minyak bisa membuat mereka lebih independent dari ketergantungan donor. Namun demikian di sekitar wilayah tempat beroperasinya EI, selalu terjadi pelanggaran HAM, dan rusaknya ekologi yang sangat parah.
CSO dan EITI
Terkait dengan persoalan di atas para peserta CSO meeting menyadari benar bahwa kondisi tersebut akan jauh lebih baik jika perusahaan EI dan pemerintah bersungguh-sungguh mengimplementasikan apa yang mereka sebut dengan EITI (The Extractive Industries Transparency Initiative) secara sukarela. Di beberapa Negara, EITI telah diusung dan diterapkan seperti yang terjadi di Timor-Timor, sementara yang lainnya sudah pada upaya “memaksa” pemerintah dan pelaku usaha EI untuk memasukkan EITI sebagai salah satu standard yang harus dikuatkan secara hukum seperti yang terjadi di Indonesia. Sementara di beberapa negara lainnya masih berjuang untuk memperkenalkan EITI ini untuk tidak hanya dilihat sebagai wacana.
Di Kamboja seperti diungkapkan Chhith Sam Ath, Direktur Ekesekutif dari The NGO Forum on Cambodia, Kamboja, ketersediaan informasi terkait keterbukaan pertanggungjawaban usaha EI itu tidak ada. Baik itu berupa informasi kontrak, dan daftar pendapatan perusahaan EI. Lebih parah lagi belum ada legal aspek atau regulasi yang bisa dijadikan “pemaksa” untuk menjalani EITI.
Sementara di Indonesia kendati EITI telah dikenal baik oleh pemerintah dan pelaku usaha EI, menurut Koalisi Nasional Publish What You Pay, Indonesia, keterbukaan masih sangatlah kurang. Mereka juga mengalami kesulitan mendapatkan data yang update di anggaran Nasional terkait dengan EI. Sementara informasi terkait kontrak usaha EI bisa disediakan namun atas dasar permintaan itu pun tanpa disertai dokumen PSC termasuk POD, WP dan anggaran.
“Yang menyulitkan lagi adalah masih adanya perbedaan pandangan antara menteri Sumber Daya dan Energi vs Menteri Keuangan serta Menteri Lingkungan,”jelas Ridaya Laodengkowe, Koordinator Koalisi Nasional Publish What You Pay, Indonesia.
Sementara di Philipina menurut Lord Byron Abadeza, Koordinator Project Transparency and Accountability Network, Philipina mengakui bahwa masih belum banyak organisasi masyarakat atau ngo yang mendorong upaya EITI. Hanya NGO local bernama Bantay Kita yang cukup eksis memperjuangkan hal ini. Byron juga menyebutkan regulasi yang mengatur EI juga sangat lemah dan payah. Transparansi hanya difokuskan pada lisensi berupa kontrak berjangka yan klausanya bersifat rahasia, operasional dan kepatuhan, pendapatan, serta endapatan belanja publik dari industri. Ini merupakan kegagalan pemerintah yang harusnya bisa menyampaikan informasi tersebut secara terbuka kepada publik. Termasuk dalam hal merasionalisasi insentif fiskal.
Sedangkan di Vietnam, menurut Pham Quang Tu, Deputi Direktur Kosultasi dan Development (CODE), Vietnam, EITI masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan sejumlah pelaku usaha EI sangat rendah partisipasinya dalam melakukan CSR. Tu juga menjelaskan bahwa memang sudah ada penigkatan kesadaran CSO dan masyarakat dalam mendorong keterbukaan akan hal ini, namun mereka selalu kesulitan dalam melakukan cek akurasinya. Kelompok CSO juga mulai mengalami kesulitan untuk mendorong isu ini ketika pemerintah justru terus membatasi ruang gerak mereka karena dianggap akan membawa pengaruh keamanan dan sektor politik.
Sementara di Timor Leste, kendati EITI telah berjalan cukup bagus diantara Negara Asean lainnya, namun diakui oleh Mericio Akara, Direktur Luta Hamutuk, Timor Leste, isu EITI masih merupakan isu yang baru. Hanya beberapa orang saja yang paham arti EITI.
“Sementara perusahaan minyak besar seperti Canoco, ENI dan Woodside sebagai operator utama tidak begitu kooperatif ketika EITI ini akan dijalankan,”jelas Akara.
Pemerintah Timor Leste dinilai juga masih lemah posisinya dihadapan perusahaan minyak ketika harus membahas untuk memisahkan atau tidak laporan pertama mereka. Sementara CSO menghadapi kendala dalam memberikan umpan balik tentang laporan akhir serta proses diseminasi. Kekurangan dalam hal melakukan proses diseminasi yaitu seperti terbatasnya akses telekomunukasi di Timor Leste.
Lesson and Learn Timor Timur
Dalam pertemuan ini, Akara juga menjelaskan bagaimana Timor Leste mempunyai sistem pengawasan ketat terhadap EI mereka terutama minyak dan gas. Sistem itu dikenal sebagai Petroleum Fund System. Keanggotaanya akan dipastikan melalui Central Bank Government yang juga memutuskan formatnya, sebagai bagian dari National Conservative Council. Peran council inilah yang disebut Akara mempunyai peran penting tidak hanya sekadar memilih keanggotaannya tetapi juga dalan pengawasan proses EITI.
Keanggotaan council ini bisa saja dilakukan mantan perdana menteri yang memilih wakilnya atau dia sendiri menjadi anggota council. Mantan presiden juga bisa memilih perwakilannya dan dia juga bisa memilih lainnya jika dia tidak bisa. Sementara 400 CSO akan memilih dua perwakilan mereka untuk menjadi anggota council di Dili.
“Peran council ini sangat penting karena merekalah yang akan menentukan dan menjamin apakah proposal pemerintah menyangkut petroleum fund itu masuk akal atau tidak, berkesinambungan atau tidak, sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang ada,” jelasnya.
Salah satu ayat dalam peraturan petroleum fund juga menyebutkan bahwa pemerintah hanya bisa mengajukan proposal tidak lebih 2% dari total. Proposal juga harus jelas bahwa dana itu hanya untuk infrastruktur bukan diperuntukkan hal lain dan mesti dipastikan kesinambungannya. Bisa saja pemerintah melakukan investasi namun hanya untuk sektor sekolah dan kesehatan. Itu pun harus jelas dan dipastikan pengembalian dana tersebut. Proses ini akan diawasi ketat oleh parlemen.
“Kendati demikian tetap saja masih ada masalah dalam implementasinya. Sebab pemerintah dapat fund dari annual budget yang dimasukkan dalam national budget. Di level inilah korupsi, nepotisme biasanya sering terjadi. Karena institusi kami ketat mengawasi di level ini.”
Dalam hal lain juga diakui selalu ada ketegangan antara Australia dan Timor menyangkut kegiatan operasional EI di offshore area. Kadang Australia mengakui area EI sebagai miliknya begitu juga Timor. Namun demikian mereka juga tidak memberlakukan tapal batas untuk 50 tahun ke depan di area ini. Namun setelah 50 tahun ke depan baru mereka bisa bicarakan perbatasan. Ini hanya untuk JPDA.
Cina dan Petronas juga mulai tertarik, namun Timor masih mempertimbangkannya mengingat resikonya sangat tinggi.
Hal lain (yang masih dipertimbangkan) yaitu tentang gas field yang disebut IOA dengan “The greater sunrise”. Namun ini pun masih dalam pembahasan dan pengkajian yang ketat. Dalam masalah ini mereka juga sering mengalami ketegangan dengan Australia tentang masalah kuantiti yang dihasilkan. Tapi dalam kontrak disebutkan baik pemerintah Timor dan Australia akan mendapatkan 50 : 50. Ketegangan lainnya dengan Australia yaitu juga menyangkut pemasangan pipa gas. Pemerintah Timor perlu pipa ke Timur, dan Australia butuh pipa untuk bawa gas ke Darwin.
“Namun di East Timor tidak ada yang datang beli gas, sehingga tidak realible untuk komersil, hingga pemerintah melakukan kesepakatan dengan Petronas. Sekarang tengah mempelajarinya. Secara komersial banyak yang berminat seperti Korea, Spanyol, Thailand, Osaka Gas Jepang, yang akan jadi konsumen kita. bahkan Cina tertarik,” jelasnya Akara.
Dalam EITI, CSO, pemerintah dan rakyat sama pandanganya dan tidak ada oposisi untuk hal ini.
“Mungkin karena kami masih Negara baru, dimana kami semua mempunyai latar belakang yang sama, pemerintah dan rakyat masih ada mantan aktivis. Tidak ada oposisi dan posisi untuk masalah gas dan minyak ini,” jelas Akara lagi.
Masalah terbaru soal EITI di Timor, tambahnya lagi, adalah laporan yang telah dilakukan menurut pengamatan CSO setempat, masih di bawah level yang detil, dan hanya umum saja.
“Kami menyerukan agar laporan harus detil. Pemerintah setuju tentang hal ini. Mereka harus konsisten melakukan komitmen keterbukaan. Namun perusahaan terkadang keberatan untuk memberikan laporan detil. Tapi kita berhasil menekan mereka untuk setidaknya melaporkan jumlah pajak mereka,”tambahnya.
Pemerintah Timor pun selalu mengumumkan ke publik tentang proses yang dilakukan termasuk aktif melakukan workshop dan diskusi kelompok setiap kali ada proyek EI datang. Sehingga publik mengetahui proses yang tengah berlangsung.
Upaya CSO untuk EITI ASEAN
Melihat kondisi tersebut CSO Asean juga telah melakukan berbagai upaya guna mendorong pelaksanaan EITI di negaranya masing-masing. Tentu saja bukan hal mudah mengingat berbagai hambatan yang telah mereka ungkapkan di atas. Legal aspek yang diinginkan pun terkadang belum tersedia dengan baik.
Contoh saja di Kamboja, peraturan hukum terkait dengan petroleum sudah tidak berlaku lagi. Hukum baru menyangkut petroleum masih sebatas draft dan itu pun belum sempat diinformasikan kepada publik. CSO Kamboja mendesak agar hal itu segera di masukkan ke Konsul Menteri sesegera mungkin.
CSO Kamboja berharap rencana keterbukaan manajemen pendapatan bisa dipublish dan melibatkan publik dalam topik yang penting seperti itu. Mereka juga akan mendorong dipublikasikannya daftar perusahaan baik yang telah diberikan jaminan izin atau masih ditunda eksplorasinya kepada publik terutama menyangkut minyak, gas, dan sumber mineral lainnya.
Di Indonesia upaya mendorong diterapkannya EITI sudah dilakukan Publish What You Pay dalam sebuah koalisai NGO Indonesia yang berfokus pada isu EI. Kini ada 35 NGO aktif yang mendorong upaya ini. Sejak 2007, mereka juga memimpun upaya lobi kepada stakeholder dari pemerintah dan perusahaan di Indonesia untuk membuka diskusi terbuka tentang EITI.
Mereka juga memberikan usulan draft tentang EITI Indonesia ke lembaga kepresidenan tentang keterbukaan pendapatan EI yang didukung pula oleh ICW. Hasilnya, pemerintah Indonesia telah “dipaksa” untuk segera mendatangani EITI.
“Sayangnya, hingga sekarang masih tertahan di meja presiden,” jelas Radaya.
Selebihnya, mereka juga ingin mendorong yang mereka sebut dengan “Beyond EITI” atau dari Vietnam meyebutnya sebagai upaya “EITI plus-plus” yang juga bisa memberikan fokus pada tanggung jawab pemerintah dan pelaku EI kepada publik tentang isu lingkungan dan masalah HAM (Hak Azasi Manusia).
Di Timor Leste, sistem EITI yang diusung harus menyertakan tiga “aktor”-nya yaitu masyarakat sipil, pemerinta juga perusahaan EI.
Sedangkan di Philipina, CSO Bantay Kita terus mendorong pelaksanaan keterbukaan yang harus dilakukan pemerintah dan sektor swasta. Namun mereka belum menemukan indikasi kuat EITI bisa diterapkan secara cepat. Tapi mereka akan memakai momentum pemilihan umum untuk memastikan orang yang terpilih sebagai presiden Philipina nanti punya perhatian terhadap masalah ini. Di Vietnam EITI akan didorong untuk dibahas di parlemen dalam waktu dekat ini.
Semua hasil yang terungkap di meeting ini rencananya akan di publish dan dishare-kan dalam Konfrensi EITI se-Asia yang akan (telah berlangsung) di Shangrila, Indonesia awal Maret ini.
Dari Oxfam Amerika dan juga RWI Internasional mengusulkan agar CSO Asean menyatukan visi dan bisa berkompromi membuka dialog dengan pihak-pihak yang selama ini dikategorikan sebagai aktor utama yang sulit menjalankan EITI, yaitu pemerintah dan perusahan EI. Kendati ada perbedaan pendapat terkait “bisa duduk dalam satu meja dan bertemu dalam satu ruang” menurut Akara dari Timor Leste, bukan berarti harus mengikuti apa kata mereka.
Namun beberapa peserta CSO meeting menandaskan bahwa hal tersebut bisa saja dimungkinkan, asalkan ada sikap yang jelas dari CSO bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah dan perusahaan untuk menghindari dan melaksanakan EITI secara baik dan benar. Mereka sepakat tidak akan bicara dalam satu meja jika masalah itu tidak disepakati.
Mereka juga sepakat bahwa sebaiknya CSO diberikan kapasitas lebih tinggi lagi sehingga mereka mempunyai posisi tawar yang baik dalam hal mendorong upaya EITI baik secara internasional maupun di negaranya masing-masing. Mereka juga menyadari benar isu ini belum dikenal secara meluas di publik bahkan di media. Karena itu mereka ingin agar media disertakan sebagai bagian penting untuk menjadi ujung tombak daya tekan mereka terhadap pelaku EI.
Terlepas dari pembahasan ini, ada hal menarik yang dilontarkan Koordinator Jatam Indonesia, Siti Maimunah.
“Ada perbedaan cara pandang kami terhadap EITI yang diusung CSO ini, dan itu sangat prinsip. Apakah jika mereka (perusahaan tambang) sudah mengeluarkan laporannya secara terbuka dan sedetil-detilnya, lalu itu bisa menjadi pengesahan bagi mereka untuk bisa mengeksplore tambang yang ada sebesar-besarnya? Padahal kita tahu bagaimana perusahaan tambang yang ada di Indonesia telah menimbulkan kerusakan bahkan bencana yang parah bagi manusia dan alam,” tandasnya. (Musfarayani).