Aryaduta, 14 April 2016
Aksi-aksi perubahan iklim memerlukan pendekatan dan solusi inovatif yang melebihi dominasi pemerintah atau yang biasa dikenal dengan top-down approach. Peran dari non-state actors (pelaku-pelaku non-pemerintah) dilihat penting untuk mengisi kesenjangan (gap) dari pencapaian ambisi aksi mitigasi antara sebelum dan sesudah tahun 2020. Laporan UNEP pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa komitmen aksi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku non-pemerintah dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 2,9 Gton CO2-eq di tahun 2020[1], hampir setengah dari komitmen aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah.[2]
Paris Agreement telah menempatkan landasan yang kuat bagi inisiatif pelaku non-pemerintah (pemerintah lokal, kota, inisiatif swasta atau bisnis, dan organisasi non-pemerintah serta komunitas) untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan tertinggi konvensi perubahan iklim, yaitu untuk membatasi kenaikan temperatur rata-rata lebih dari 2 derajat. Para pelaku non-pemerintah dapat melakukan aksi mitigasi dengan mengisi kesenjangan yang disebabkan oleh kurangnya aksi yang dilakukan oleh pemerintah yang tergabung di dalam UNFCCC.
Laporan UNEP di tahun 2015 telah mengidentifikasi sekitar 180 inisiatif kerja sama internasional, mencakup lebih dari 20.000 organisasi yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK melalui berbagai macam aktivitas. Pelaku inisiatif-inisiatif ini termasuk di dalamnya adalah bisnis dan perusahaan, kota dan regio, serta inisiatif sektoral. Walau demikian, laporan yang sama juga mencatat bahwa terdapat beberapa area lain yang belum dapat diatasi melalui aksi-aksi spesifik, dikarenakan lingkup inisiatif yang sangat luas dan beragam; mulai dari dialog tingkat tinggi hingga aksi-aksi mitigasi yang konkrit.
Institute for Essential Services Reform (IESR) didukung oleh Climate Knowledge Development Network (CDKN) mengadakan semiloka pada tanggal 14 April 2016 yang lalu, sebagai langkah pertama untuk mengerti kealamian (nature) dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh para pelaku non-pemerintah (NSA) yang ada di Indonesia, bagaimana perkembangannya, dan pada saat yang bersamaan berupaya untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada terkait dengan aksi-aksi mitigasi yang dilakukan. Beberapa pertanyaan dasar yang diharapkan dapat terjawab melalui semiloka ini antara lain:
- Siapa dan di mana lokasi kerja mereka (bisnis, kelompok masyarakat sipil, kota atau daerah, inisiatif sektoral?)
- Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku-pelaku non-pemerintah ini?
- Bagaimana inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan dapat dikaitkan dengan UNFCCC?
- Apa yang menjadi target dari NSA tersebut dan apa yang telah dicapai (dalam hal penurunan emisi)?
Mengerti kealamian dari inisiatif NSA ini akan sangat berguna untuk pengembangan kerangka dalam rangka mengintegrasikan NSA ke dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang diperlukan untuk diajukan sesuai dengan Paris Agreement, serta untuk merancang mekanisme yang sesuai untuk tracking dan MRV, sehingga nantinya dapat dimasukkan ke dalam berbagai bentuk komunikasi Indonesia kepada UNFCCC, baik dalam bentuk biennial update report maupun national communication.
Semiloka ini terdiri dari tiga sesi dan menghadirkan beberapa narasumber, itu:
- Sesi 1: Framing session: Fabby Tumiwa, Institute for Essential Services Reform (IESR)
- Sesi 2: Aksi-aksi mitigasi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku non-pemerintah:
- Ibu Sinta Kaniawati, Unilever
- Bapak Irvan Pulungan, ICLEI
- Ibu Indra Sari Wardhani, WWF Indonesia
- Sesi 3: Menjajaki kerangka MRV yang potensial di Indonesia:
- Bapak Hari Wibowo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Bapak Dr. Hardiv Situmeang, KNI-WEC
- Bapak Dicky Erwin Hendarto, Sekretariat JCM di Indonesia
- Bapak Paul Butarbutar, South Pole
[1] UNEP 2015. Climate commitments of sub-national actors and business: A quantitative assessment of their emission reduction impact. United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi

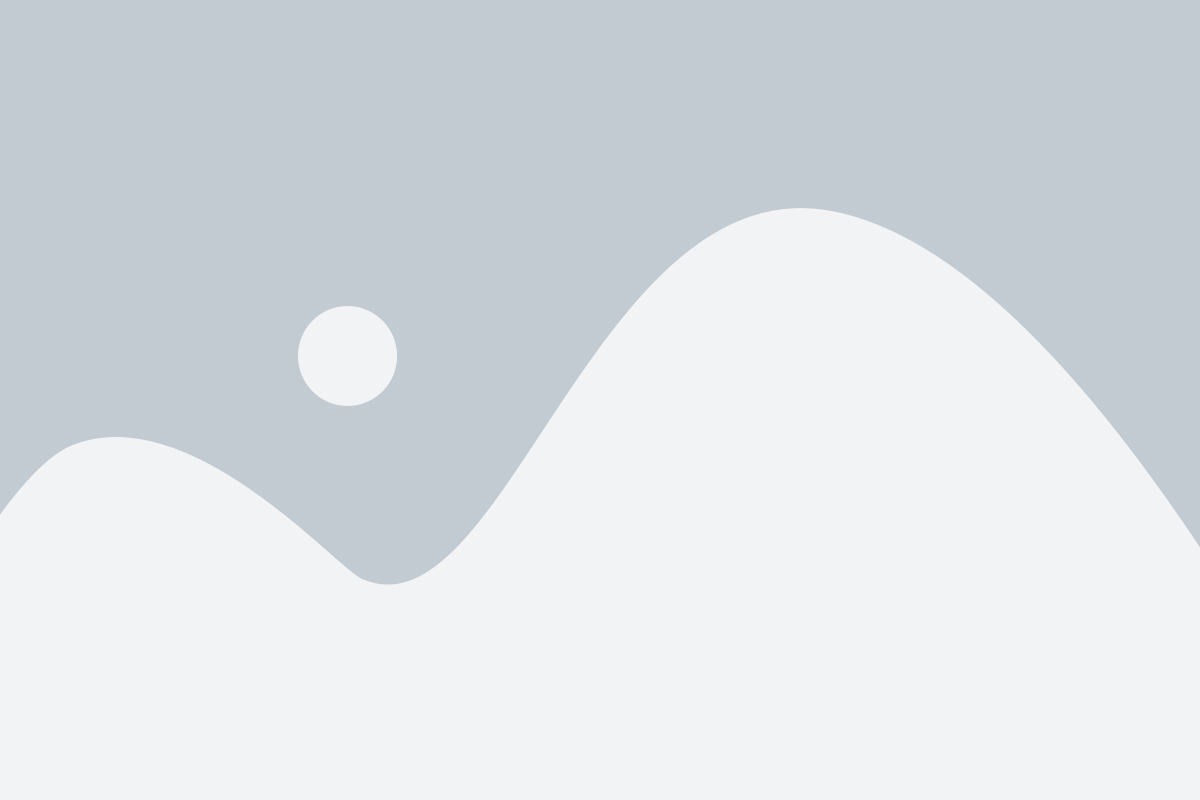
 Untungnya proses negosiasi yang dilakukan secara maraton oleh Presiden COP, yang juga Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius sejak Sabtu siang hingga malam berhasil mengakomodasi kepentingan dan posisi berbagai negara dan blok negosiasi. Titik temu dan kesepahaman berhasil tercapai terutama untuk isu-isu yang masih alot dibahas hingga Sabtu pagi, diantaranya: target temperature global, diferensiasi, fleksibilitas dan dukungan bagi negara berkembang untuk melakukan aksi.
Untungnya proses negosiasi yang dilakukan secara maraton oleh Presiden COP, yang juga Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius sejak Sabtu siang hingga malam berhasil mengakomodasi kepentingan dan posisi berbagai negara dan blok negosiasi. Titik temu dan kesepahaman berhasil tercapai terutama untuk isu-isu yang masih alot dibahas hingga Sabtu pagi, diantaranya: target temperature global, diferensiasi, fleksibilitas dan dukungan bagi negara berkembang untuk melakukan aksi.

 Kepala delegasi Filipina secara emosional meminta kepada para peserta konferensi untuk “mengakhiri kegilaan” pemanasan global yang memicu iklim ekstrim. Mengutip bahwa topan Haiyan adalah badai terburuk dan terdahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah.
Kepala delegasi Filipina secara emosional meminta kepada para peserta konferensi untuk “mengakhiri kegilaan” pemanasan global yang memicu iklim ekstrim. Mengutip bahwa topan Haiyan adalah badai terburuk dan terdahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah.

