Oleh: Dwitho Frasetiandy (Walhi Kalsel)
“Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang tamak”. (Mahatma Gandhi).
Ungkapan diatas kiranya dapat sedikit menggambarkan bagaimana pengelolaan sumber daya alam di negeri ini dan juga Kalimantan Selatan. Kerusakan, kerakusan merupakan sesuatu yang saya kira merupakan kata-kata yang sangat pas bagi mereka yang terus-menerus menggerus sumber daya alam yang ada tanpa memeperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Padahal logikanya dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ini akan mampu menjadi penopang perekonomian dan juga sebagai penggerak perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, namun harapan itu ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi sekarang. Mengambil sebuah kata dari para ekonom dunia “the resource curse atau the paradox of plenty”, yang merupakan gambaran bahwa sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam namun ternyata kekayaan itu bukan menjadi sebuah kekayaan bagi kita semua namun makah berubah menjadi bencana lingkungan dan sosial.
Produksi batubara Kalsel yang mencapai 78 juta ton/tahun, jumlah yang sangat lah besar, namun pada kenyataannya saat ini 70% batubara itu diekspor ke luar negeri, 29% dikirim ke pulau jawa, dan yang semakin ironis adalah keuntungannya tidaklah berputar di kalsel namun hanya dinikmati segelintir orang saja di Jakarta dan sebagian di kalsel. Kalau kita hitung secara matematis, dengan harga batubara 100 dollar per metrik ton, batubara kalsel dapat menghasilkan keuntungan mencapai 8 trilyun/tahun atau 4 kali lipat dari APBD yang cuma” 1,8 trilyun/tahun.
Namun ternyata yang didapat daerah tidak lah sebanyak yang kita pikirkan, menurut pemerintah kalsel hasil royalti yang didapat dari batubara “hanya” 85 milyar saja pada tahun 2008 lalu, padahal keuntungan yang didapat dari ekspor batubara kalsel di triwulan awal tahun 2009 ini saja mencapai u mencapai 1,4 trilyun rupiah. Wow, sebuah angka yang sangat fantastis untuk 3 bulan pertama saja, bahkan jauh melampaui APBD Kalsel. Tapi yang didapat daerah hanya lah “seujung kuku” dari yang keuntungan yang dinikmati oleh para pengusaha pertambangan itu.
Kesejahteraan jadi kata yang diucap berulang-ulang oleh pemerintah dan pelaku tambang, saat membicarakan penerukan batubara. Mereka bilang peningkatan produksi batubara akan meningkatkan pemasukan asli daerah (PAD) dari sektor ini. Naiknya PAD seringkali diasumsikan dengan naiknya tingk at kesejahteraan rakyat. Namun apakah klaim ini benar adanya?
Pertambangan, Jauh Kesejahteraan = Kemiskinan
Pendapatan sektor pertambangan diatur dalam UU No. 33/2004, yang menyebutkan penerimaan iuran tetap pertambangan umum untuk pusat sebesar 20% dan 80% untuk daerah (16% propinsi dan 64% kabupaten/kota), penerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum terdiri dari 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah (16% untuk propinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, 32% untuk kabupaten lainnya). Namun kebijakan ini tidak cukup memuaskan daerah karena penyerahan cenderung terlambat dan ketidak pastian jumlah yang diterima.
Selain itu, untuk mendapatkan dana iuran ini teranyata tak mudah. PT. Arutmin Indonesia (Bumi Resources) menunggak sampai 3 tahun yang mencapai USD 13 juta atau setara Rp 13 miliar ke Pemprov Kalsel. Tunggakan PT Arutmin itu merupakan akumulasi dari perhitungan royalti tahun 2004 dan tahun 2005. Termasuk denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran royalti tersebut.
Sebelumnya total tunggakan royalti perusahaan itu mencapai USD 30 juta. Rupanya, tunggakan ini terus berlanjut tahun 2004 mencapai USD 29 juta, hingga dibayar tahun 2005 sebesar USD 23 juta, sehingga tersisa USD 5 juta. Ternyata, tunggakan itu berlanjut lagi tahun 2005 hingga besarannya mencapai USD 16 juta. PT Bahari Cakrawala Sabuku sempat menunggak royalti hingga 2005 mencapai USD 4,5 juta. Kemudian, PT Antang Gunung Meratus sempat ‘ngutang’ USD 714 ribu. Hal serupa juga dilakoni PT Sumber Kurnia Buana sempat menunggak royalti sebesar USD 3,7 juta, PD Baramarta sebesar USD 5,9 juta, PT Tanjung Alam Jaya USD 583 ribu, dan PT Baramulti Sukses Sarana USD 321 ribu.
Kabupaten Tanah Laut yang dikenal sebagai daerah kaya batubara ternyata mendapatkan royalti batubara tahun 2005 adalah Rp. 8,014 milyar, sumbangan Pihak ketiga sebesar Rp.10,321 milyar sehingga total pendapatannya menjadi Rp. 18,336 milyar. Sedangkan tahun 2006 (data sampai dengan Juli) sudah diperoleh Rp. 10,145 milyar. Tanah laut berupaya mencari peluang meningkatkan pendapatannya dari sektor batubara dengan meningkatkan besaran sumbangan pihak ketiga pengusaha batubara, dari Rp 1000 menjadi Rp 2000 untuk setiap ton batubara yang dikeruk. Selain itu, sumbangan diharapkan dari didapat dari pengalihan wewenang pembuatan surat keterangan asal barang (SKAB) dari gubernur kepada bupati. Peluang lainnya dari bidang transportasi dan pelabuhan melalui Perda 7/2003, tentang ragam pungutan (retribusi) atas seluruh kegiatan kepelabuhan. Di antaranya, retribusi jasa tambat, jasa labuh, jasa pemanduan, jasa penumpukan barang, dan jasa sewa perairan. Nominal retribusi jasa alur sesuai Perda nomor 7 yaitu Rp7.500 per ton batubara.
Kondisi diatas tidak jauh beda didapat pada penilaian IPM tahun 2006, dimana Kalsel berada pada peringkat 26 dari 33 propinsi di Indonesia. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun 2006, hanya 4,7 persen atau di bawah rata-rata nasional yang mencapai 6 persen. Angka itu juga lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun 2005, yang mencapai 5 persen. Bila dicermati lebih jauh, sejak tahun 1999 hingga 2005, ranking IPM Kalsel secara konstan menurun. Urutan 21 pada tahun 1999, kemudian berada pada urutan 23 di tahun 2002, 24 di tahun 2004 dan urutan 26 di tahun 2005.
Apa yang terjadi di tataran propinsi juga terjadi di tataran kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Bumbu, yang notabene sumbangan sektor pertambangan selama tiga tahun terakhir PDBR berlaku rata-rata di atas 35% (tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di kalsel) ternyata IPM Kabupatennya berada pada urutan 10 dari 13 Kabupaten/kota lainnya. Bahkan sangat jauh dibandingkan dengan IPM Banjarbaru yang nyaris hanya mengandalkan sektor jasa dan perdagangan dalam PDBRnya.
Sesungguhnya, berdasarkan Ilmu Ekonomi suatu investasi idealnya harus membawa efek penciptaan lapangan kerja dan efek ganda lainnya yang positif, sebagaimana argumentasi yang selalu disampaikan para bupati saat mereka akan mengeksplotasi sumberdaya alam di daerah mereka. Argumentasi itu mereka kemukakan karena mereka tidak pernah tuntas menyelesaikan masalah pengangguran. Padahal agar suatu investasi dapat mencapai keadaan tersebut banyak syarat dan konsekuensi lain yang harus diperhatikan. Hal ini tampaknya tidak terjadi dalam investasi tambang batubara.
Investasi pertambangan batubara tidak akan mensejaterakan masyarakat, kalau hanya ditinjau dari keuntungan penciptaan lapangan kerja dan efek ganda. Karena investasi bisa saja ditanam pada sektor ekonomi lain bukan pertambangan batubara, dan sudah pasti juga akan menciptakan lapangan kerja dan efek ganda lainnya. Dengan demikian argumentasi penciptaan lapangan kerja dan efek ganda tersebut sangat kurang tepat.
Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari serapan tenaga kerja. Sebagaimana disebutkan terdahulu, masalah pengangguran belum tuntas di Kalimantan Selatan. Dari 3.250.100 orang penduduk Kalimantan Selatan (Data Tahun 2005), 1.468.590 orang diantaranya bekerja atau sekitar 45%.
Sektor yang paling tinggi menyerap tenaga kerja adalah pertanian, yang menyerap 741.298 orang atau 51 persen tenaga kerja. Sektor pertambangan yang sangat dominan dalam menghasilkan nilai tambah (rangking 2), output (rangking 1), dan investasi (rangking 2), ternyata hanya mampu menyerap tenaga kerja 33.738 orang atau dua persen. Tenaga kerja inipun kebanyakan berasal dari luar desa bahkan banyak dari mereka berasal dari luar provinsi.
Industri Ekstraktif Harus Terbuka Kepada Publik
Rezim ketertutupan informasi atas penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif akan terpatahkan. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010, kini publik berhak tahu berapa besar penerima negara dari industri ekstraktif. Industri ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi, ditambah dengan sudah berlakunya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentunya semakin menguatkan kita bahwa informasi terkait industry ekstraktif di kalsel harus dibuka selebar-lebarnya.
Perpres No. 26 Tahun 2010 mengatur tentang transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diterima dari industri ekstraktif, kebijakan transparansi ini akan menjadi angin segar dalam rangka memperbaiki tata kelola industri ekstraktif. Selama ini, industri migas dan pertambangan relatif sangat tertutup.
Perpres ini merupakan adopsi sekaligus pertanda keikutsertaan Indonesia dalam Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Perpres 26 bisa dikatakan sebagai langkah strategis untuk menguraikan aliran pendapatan negara dari sektor industri ekstraktif. Pendapatan negara selama ini disumbang 32 sampai 35 persen dari industri ekstraktif. Celakanya, sumber pendapatan dari migas dan tambang telah lama menjadi sumber konflik antara Pusat dan Daerah. Terutama mengenai dana bagi hasil.
Selama sembilan tahun masa desentralisasi sekitar 7.000 Kuasa Pertambangan (KP) diterbitkan Pemerintah. Cuma, tak terdata dengan jelas berapa pendapatan dan berapa manfaat riil yang diperoleh negara dari migas dan tambang. Yang ada justru informasi tentang kerusakan ekologis akibat pengelolaan tambang yang tak tertata dengan baik.
Masyarakat juga akan tahu perusahaan mana saja yang bergerak di industri ekstraktif, sekaligus tercatat data berapa pendapatan yang diperoleh negara dari perusahaan. Masyarakat juga dapat mengetahui berapa banyak volume migas yang diekspor dan berapa yang dipersiapkan untuk kebutuhan dalam negeri. Seperti diketahui, Menko Perekonomian Hatta Radjasa sudah berkali-kali menekankan pentingnya mengedepankan kebutuhan migas domestik ketimbang ekspor.
Namun bagaimanapun juga inisiatif EITI yang diperkuat dengan Keluarnya Perpres No.26 tahun 2010 ini bukan hanya satu-satunya cara untuk meminimalisir praktek-praktek korupsi di sector pertambangan dan industry ekstraktif lainnya, tapi setidaknya mampu menjadi langkah awal di Kalimantan Selatan untuk mencegah adanya praktek korupsi di sector ini dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam industry ekstraktif di Kalimatan Selatan.
Kebijakan pemerintah yang lebih transparan dalam industri ekstraktif bukan saja mutlak dibutuhkan guna mengurangi tingkat korupsi dan manipulasi hasil pendapatan yang seharusnya diterima negara, tetapi dapat memperbaiki iklim investasi di bidang ini. Namun, yang lebih penting, masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dibayarkan industri kepada negara, negara menerima berapa, dan untuk apa saja. Pertanyaannya, bisakah Pemerintah melakukan hal ini. Jika tidak, sedih sekali masyarakat kalsel, sudah tidak mendapat kemakmuran secara ekonomi, masih tidak diberi informasi atas pendapatan dari hasil pengelolaan industri berbasis sumber daya alam.
Pertanyaan yang perlu dikemukakan pula dari semua fakta ini adalah “ untuk siapa sebenarnya energy dan indutri ekstraktif tersebut selama ini? Kita melayani siapa?”. Bayangkan 70 % dari 78 Juta Ton produksi batu bara kalsel di ekspor ke luar negeri. hanya sisa dari itu lalu melayani kepentingan domestik, perdebatan kuota-antikuota pemenuhan kebutuhan domestik ternyata hanya menjadi debat kusir, sementara ekspor terus melenggang tanpa halang-rintang. maka terjawablah sudah pertanyaan “untuk siapa energy dan batu bara kita selama ini dan kita melayani siapa”.
Bukan kah seharusnya apa yang terkandung didalam tanah Kalimantan Selatan menjadi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kita dan generasi yang akan datang, bukan dengan cara keruk habis seperti ini. Sehingga pertanyaan apakah batubara itu mensejahterakan, bukan lagi sebuah mitos belaka.

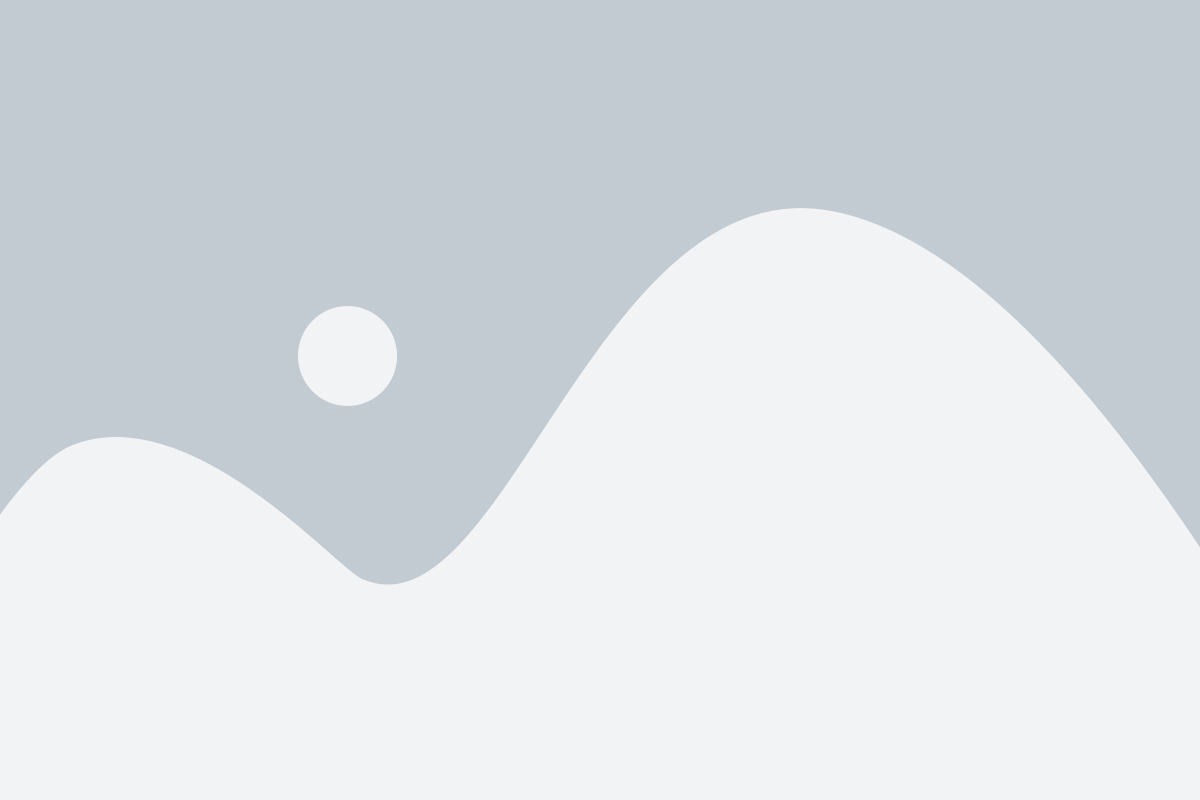

 Cukup puas saya dengan hasil dan tampilan poster tersebut. Saya berharap semoga poster tersebut bisa dipilih sebagai yang terbaik. Maka saya pun bisa melakukan perjalanan dengan tenang ke Australia guna mengikuti konferensi tersebut.
Cukup puas saya dengan hasil dan tampilan poster tersebut. Saya berharap semoga poster tersebut bisa dipilih sebagai yang terbaik. Maka saya pun bisa melakukan perjalanan dengan tenang ke Australia guna mengikuti konferensi tersebut.

