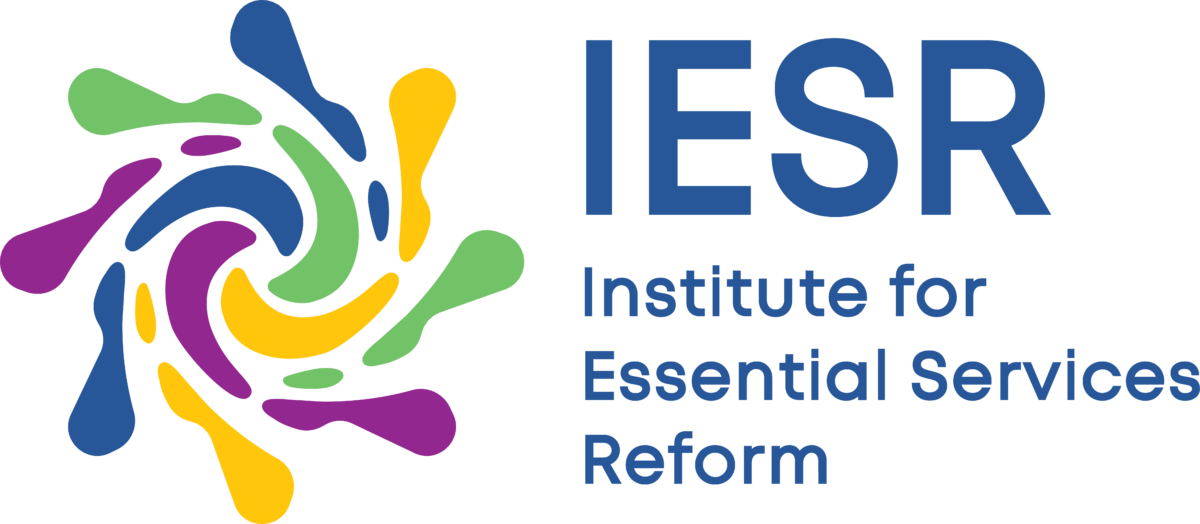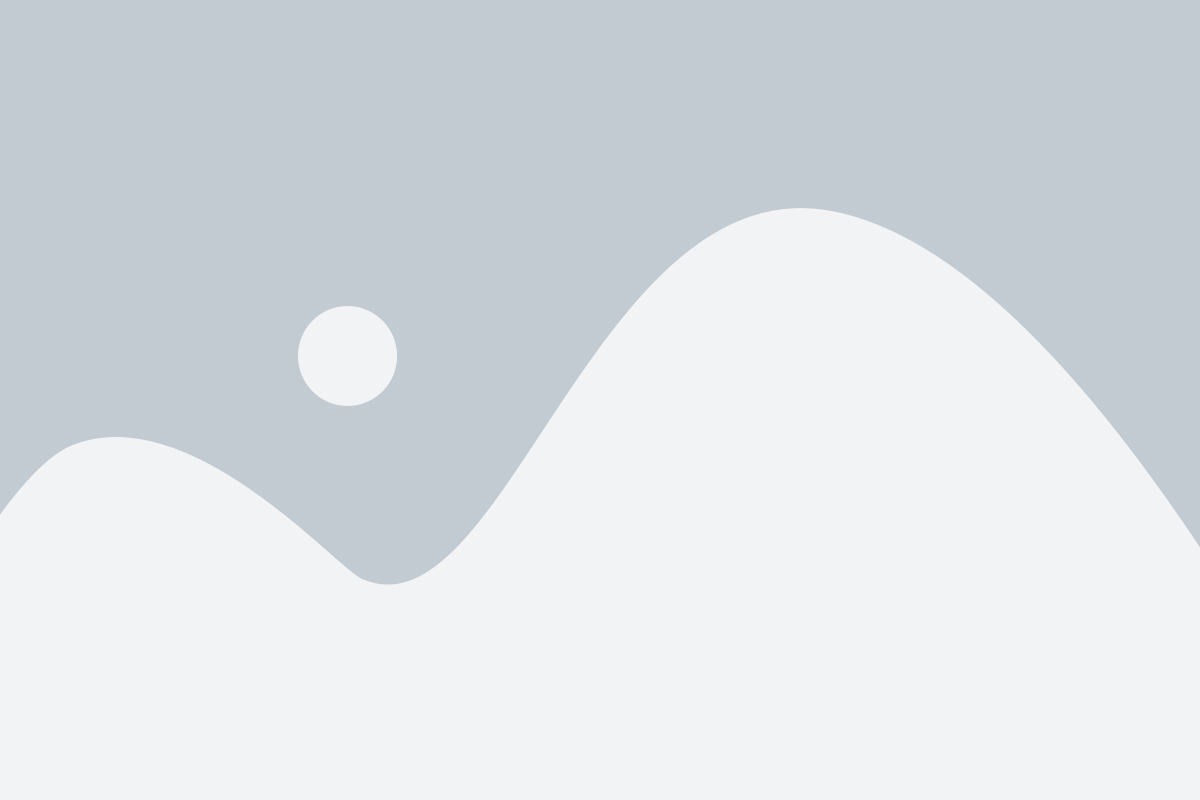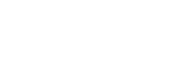Selama dua hari Kompas menjadikan pertambangan sebagai tema besar berita-berita mereka. Dengan apik Kompas mengangkat sejumlah isu yang amat meresahkan di sektor pertambangan. Sebut saja maraknya pertambangan emas yang telah mengubah topografi pulau Buru dan membuat resah masyarakat adat di sana (Kompas, 20/02). Atau masalah izin-izin pertambangan di daerah yang dianggap hanya menguntungkan pejabat sementara meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan masalah bagi masyarakat di sekitar tambang. Tulisan ini kemudian berupaya untuk mengajak saudara melihat gambaran yang lebih besar mengenai masalah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Potensi di sektor pertambangan serta perminyakan Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Kedua sekor ini, terutama sektor migas, telah memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia. Untuk sektor migas, sekalipun pengusaha dan investor mengeluhkan iklim investasi yang tak kondusif, sektor ini tetap menarik minat para pengusaha untuk tetap berusaha di Indonesia. Buktinya, beragam perusahaan raksasa tak lantas pergi dan meninggalkan ladang-ladang minyak Indonesia.
Di sektor pertambangan, mengendurnya kontrol pusat sebagai akibat desentralisasi telah mendorong munculnya ribuan konsesi tambang. Ribuan hektar tanah di berbagai daerah di Indonesia, terutama Kalimantan, tanah dibongkar untuk mendapatkan emas, tembaga, timah, batubara, dan banyak lagi. Hutan-hutan pun turut ditebang, tak pandang bulu terkait dampak bagi generasi di masa yang akan datang. Pasalnya sederhana saja, harta karun Pertiwi tersimpan rapi di dalam perut hutan.
Di banyak negara, terutama negara-negara berkembang, praktik keruk-mengeruk perut bumi, yang disebut dengan industri ekstraktif ini merupakan kegiatan ekonomi yang banyak diminati. Sebagian dibutuhkan untuk menyediakan suplai energi, seperti minyak dan batubara. Sebagian lagi karena memang komoditas barang galian seperti emas dan batubara telah menarik minat terkait dengan keuntungan yang didapatkannya .
Sejumlah negara mampu mentransformasi kekayaan menjadi mesin pelumas perekonomian yang membuat masyarakatnya kaya dan sejahtera. Mari kita telisik Arab Saudi dan juga Qatar atau Dubai misalnya. Penemuan minyak di negara-negara tersebut mampu mentransformasi padang gurun menjadi gedung-gedung beton bertingkat dan infrastruktur mengagumkan lainnya. Perputaran roda ekonomi berlangsung sangat cepat dan pertumbuhan indeks pembangunan manusia (HDI) negara-negara tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Negara lainnya yang patut mendapatkan applaus adalah Brunei Darussalam, Malaysia, dsb.
Hal yang berbeda terjadi di Indonesia dan sejumlah negara miskin dan berkembang seperti sejumlah negara-negara di Afrika dan juga Timur Tengah. Kekayaan alam di negara-negara ini bukannya menyalurkan kesejahteraan ke tangan masyarakatnya, justru menjadi biang keladi bagi kemiskinan yang semakin merajalela.
Fenomena tersebut acap disebut dengan kutukan sumber daya alam, atau resource curse
Resource curse merupakan sebuah fenomena dimana daerah-daerah atau negara-negara yang kaya sumber daya alam mengalami sebuah kondisi dimana pertumbuhan perekonomian mereka tidak sepesat daerah atau negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekayaan alam yang mereka miliki justru membawa masyarakat yang hidup dalam daerah atau negara tersebut kesebuah kondisi yang penuh dengan konflik dan masyarakatnya hidup di dalam garis kemiskinan. . Secara sederhana, kutukan sumber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam menterjemahkan kekayaan alam menjadi alat pendorong kesejahteraan masyarakat.
Ada sejumlah kondisi yang menyebabkan suatu daerah atau negara dapat mengalami hal tersebut, yang pertama adalah sifat atau nature dari industri ekstraktif itu sendiri yang sangat tertutup. Di masa-masa terdahulu, mulai dari awal perencanaan hingga eksplorasi dan eksploitasi, semuanya serba tertutup. Sangat sulit untuk memperoleh akses pada data-data penting seperti kontrak, dokumen izin, dsb. Apalagi data pembayaran dari perusahaan kepada negara. Sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara dari hasil ekstraksi yang mereka lakukan.
Dampaknya adalah, seluruh rantai pengelolaan sumber daya ini mulai dari pemberian izin hingga pengelolaan dan pembagian keuntungan kepada negara menjadi sangat rentan terhadap praktik-praktik korupsi. Pemberian izin dapat dilakukan dengan kongkalikong antara pejabat dan pengusaha.
Jika pendapatan negara/daerah dari sektor tersebut tidak dapat diterima secara maksimal dan dikelola dengan baik, maka pendapatan tersebut tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan daerah penghasil tersebut dan danya tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek guna pengentasan kemiskinan.
Fenomena kutukan sumber daya alam secara mikro bisa kita amati di Indonesia. Di beberapa wilayah, justru kawasan-kawasan yang punya sumber daya alam melimpah terbukti memiliki HDI yang cukup rendah. Lihat saja Riau dengan produksi minyak terbesar, lalu Aceh dengan gas nya dan Papua dengan tambang tembaga emasnya di Grasberg, ketiga daerah tersebut menjadi pusat kantong-kantong kemiskinan dan angka buta huruf cukup tinggi di Indonesia.
Secara makro, pendapatan dari sektor ekstraktif tersebut memang berkontribusi bagi stabilitas angka-angka di deretan kolom APBN, tapi secara mikro, kekayaan tersebut ibarat racun bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang. Ada segudang penjelasan mengapa kekayaan alam tersebut tidak bisa ditransformasi menjadi kesejahteraan masyarakat. Salah satu jawabannya adalah pengelolaan yang serampangan serta tertutupnya akses informasi dari masyarakat luas yang mendorong tingginya tingkat korupsi. Masyarakat internasional mengenal fenomena ini dengan terminology lack of good governance and transparency.
Good governance telah menjadi salah satu mantra ajaib yang banyak didengungkan dalam teori pembangunan modern. Kata governance yang mengacu pada ‘tata kelola’ disebut-sebut sebagai formula rahasia yang menentukan kemajuan atau kemunduran suatu negara. Apa sebenarnya governance atau tata kelola ini? Badan PBB yang khusus mengurusi isu pembangunan di Asia dan Pasifik (UNESCAP) mendefenisikan governance sebagai “the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented). Proses pembuatan kebijakan dan sebuah proses di mana keputusan diimplementasikan.” Terminologi good governance kemudian mengacu pada segala standard positif atau baik yang dilihat ketika semua kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Hal ini mencakup proses pemilihan pemimpin, pemilihan eksekutor, proses pembuatan anggaran, dll.
Kekayaan ini tak bisa serta merta dapat langsung diganti. Ini adalah hutang bagi anak cucu di masa yang akan datang. Salah satu aspek penting dalam menggolkan pengelolaan yang baik ini adalah memastikan bahwa semua kebijakan dibuat dan diimplementasikan dengan transparan. Ya, transparansi adalah poin penting dalam upaya menuju tata kelola yang baik. Ketika tata kelola kebijakan mulai dari perencanaan hingga implementasi berjalan dengan mulus, lepas dari kepentingan oknum-oknum tertentu. Dengan transparansi dan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik, masyarakat sipil dan pihak-pihak yang menaruh hati pada permasalahan ini dapat menjadikan data dan akses terhadap informasi sebagai senjata pengawasan. Dibutuhkan kerja keras dari semua pihak untuk bisa membongkar ulang segala aturan dan mekanisme serta pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.