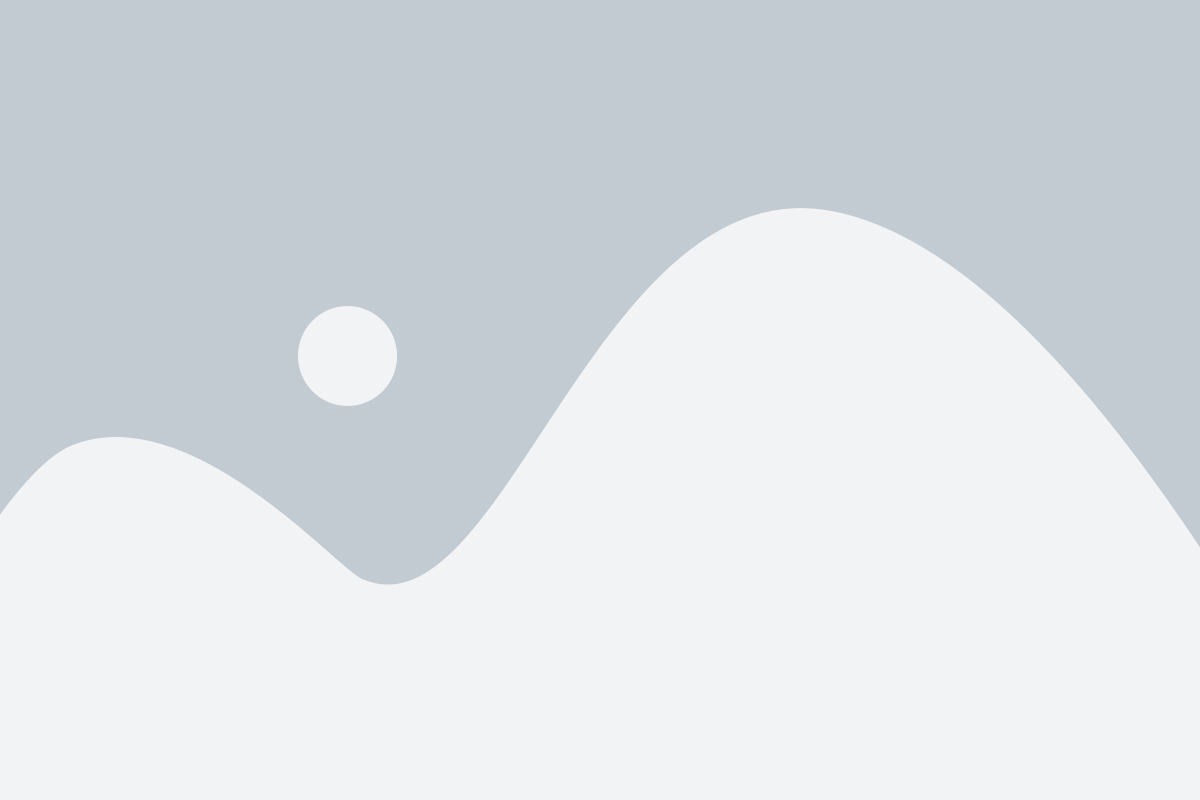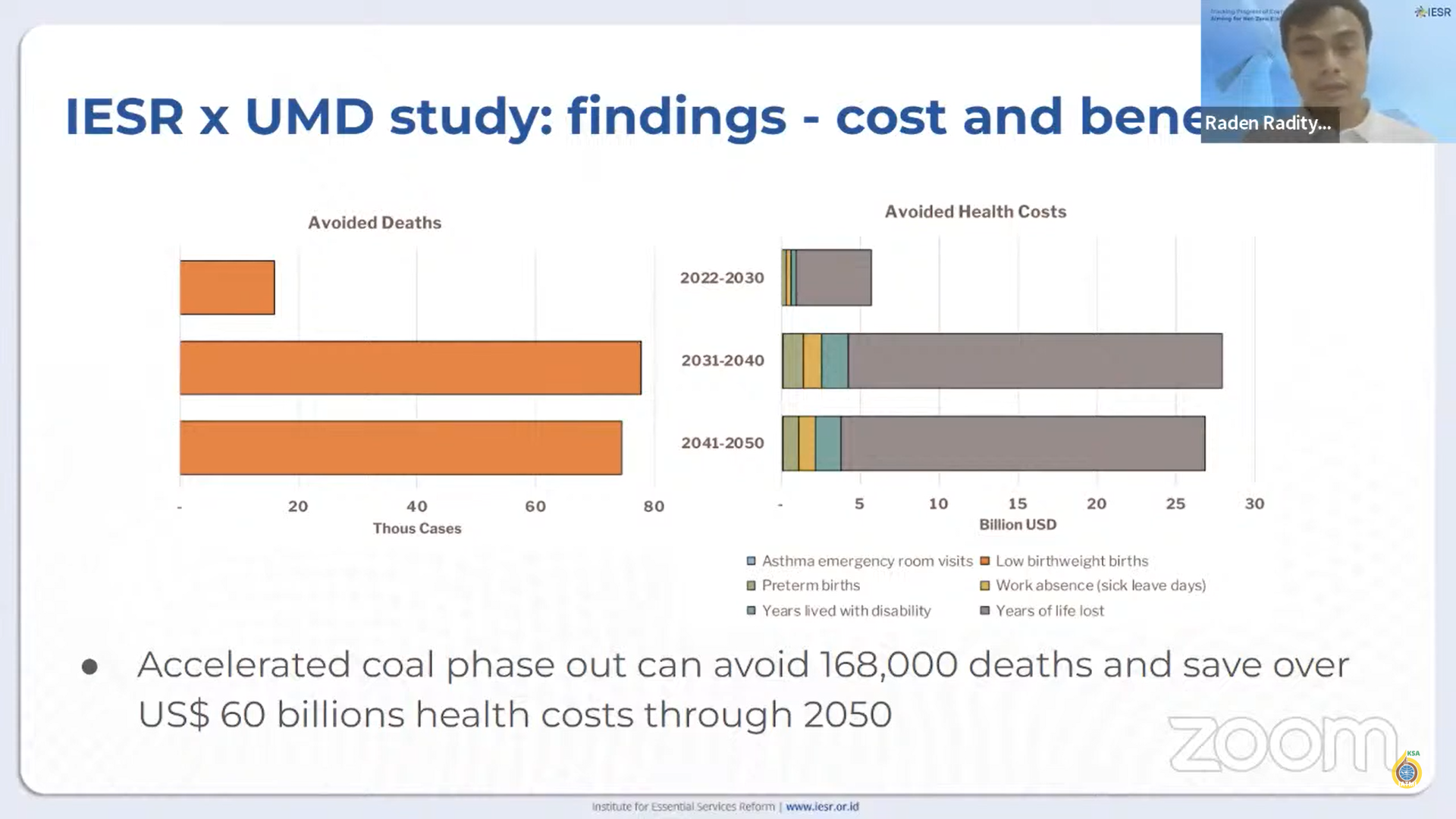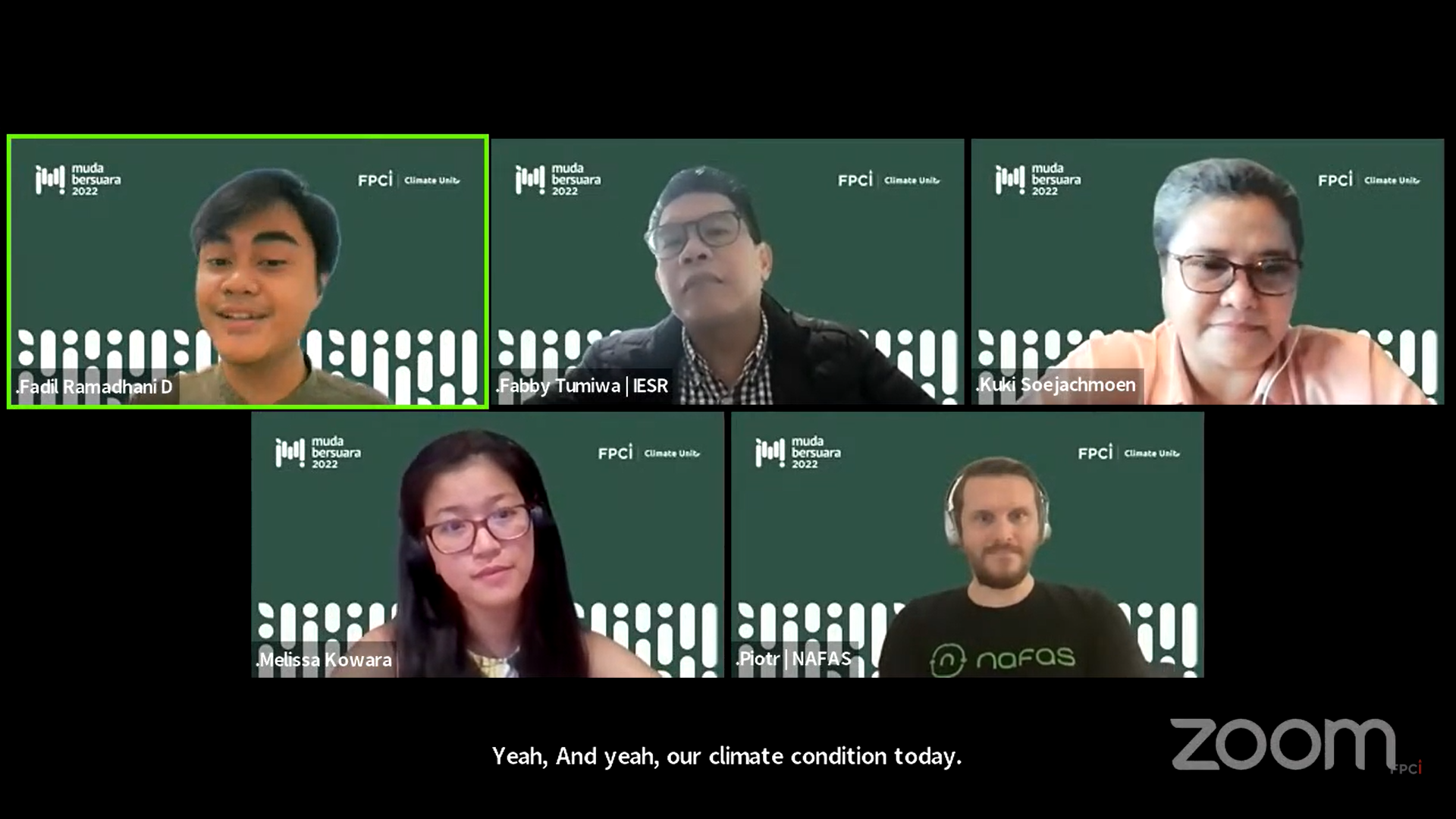Jakarta, 19 Desember 2022 – Peranan energi menjadi penting untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. Untuk itu, pengelolaan energi meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu. Terlebih Indonesia telah berkomitmen sesuai Persetujuan Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, dengan target sebesar 31,89% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri dan target sebesar 43,2% dengan bantuan internasional.
Berdasarkan studi Deep Decarbonization of Indonesia’s Energy System yang dikeluarkan oleh IESR, Indonesia mampu untuk mencapai target Persetujuan Paris netral karbon pada 2050. Dekade ini menjadi penting, karena Indonesia harus segera mencapai puncak emisi di sektor energi pada tahun 2030 dan mendorong bauran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan mencapai 45%.
Pembangunan sektor energi terbarukan menjadi aksi mitigasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendukung energi yang berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia terus menggencarkan penggunaan energi terbarukan. Energi surya menjadi salah satu pilihan jenis energi terbarukan yang terus didorong penggunaannya di Indonesia.
Melansir Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Konversi Energi Surya dan Angin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi matahari melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Teknik pemanfaatan energi surya pertama kali ditemukan oleh peneliti asal Prancis, Edmund Becquerel pada tahun 1839. Meskipun letak matahari sekitar 149 juta kilometer dari bumi, namun pancaran sinarnya bisa digunakan menjadi sumber energi terbarukan. Sinar matahari tersebut dikonversikan menjadi energi listrik menggunakan teknologi fotovoltaik (photovoltaic/pv) yang terdapat di dalam panel surya.
Panel surya merupakan kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Konversi energi surya menjadi listrik berawal saat sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi untuk alat elektronik.
Berdasarkan laporan Indonesia Solar Energy Outlook 2023 yang dikeluarkan IESR, tenaga surya memainkan peran penting dalam dekarbonisasi mendalam di Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat pada 2050, setidaknya 88% dari kapasitas daya terpasang akan berasal dari tenaga surya pada 2050. Sayangnya, penggunaan tenaga surya di Indonesia baru mencapai 0,2 GWp dari kapasitas terpasang dan hanya menghasilkan kurang dari 1% dari total pembangkit listrik pada akhir tahun 2021.
Namun demikian, kemajuan energi surya Indonesia terlihat dari turunnya harga listrik PLTS yang diperoleh melalui perjanjian pembelian tenaga listrik (power purchase agreement (PPA)) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta. Harga PPA PLTS telah turun sekitar 78% dari US$0,25/kWh menjadi US$0,056/kWh antara rentang 2015 dan 2022. Untuk itu, IESR memprediksi setidaknya dengan bertambahnya proyek PLTS skala besar, turunnya harga modul surya, dan membaiknya iklim investasi, harga investasi PLTS per unit akan terus turun, mendekati trend harga di dunia. Selain itu, dari sisi perkembangan project pipeline untuk PLTS skala besar, saat ini terdapat delapan proyek dengan total kapasitas 585 MWp (telah dilelangkan).